Konsep Adab dalam Tafsir Pancasila (Draft)
Adab
merupakan salah satu konsep yang penting untuk digali oleh bangsa Indonesia
karena ia terdapat di dalam Pancasila yang berstatus sebagai dasar negara,
“dasar filsafat” (philosophische grondslag) negara, “pandangan hidup” (Weltanschauung),
atau “pokok kaidah fundamental negara” (Staatsfundamentalnorm).[1]
Penggalian konsep adab itu tentunya tidak boleh dipisahkan dari kerangka utuh
tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan nilai yang mengandungnya. Namun,
penyelidikan makna adab dalam kerangka tafsir Pancasila itu tidaklah mudah
dilakukan, mengingat corak keredaksian kelima silanya yang bermakna luas dan
secara inheren memicu keragaman tafsir, juga berbagai pertentangan, tarik-ulur interpretasi,
dan polemik diskursif yang menyertainya sejak masa perumusannya.[2]
Oleh
karena itu, perlu ditinjau, yang pertama, pelbagai perdebatan terkait
penafsiran dan penerapan Pancasila dalam catatan sejarah yang terangkum dalam
sejumlah isu, yaitu (1) Pancasila dan Islam; (2) Pancasila dan Marxisme /
Komunisme; (3) Pancasila dan Liberalisme-Kapitalisme; (4) Pancasila dan Demokrasi;
dan (5) Pancasila pasca-Reformasi. Tinjauan poin ini dilakukan mengingat
drastisnya pergeseran polar dalam pemahaman, penafsiran, dan penerapan Pancasila
sejak awal Orde Lama (era Konstituante dengan demokrasi yang liberal), era
Demokrasi Terpimpin yang condong pada Marxisme / Komunisme, era “Demokrasi
Pancasila” Orde Baru yang condong ke Barat, hingga era Reformasi dengan
berbagai dinamikanya yang khas.
Kedua,
karena kata adab terdapat pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang
adil dan beradab, maka makna dasarnya dalam frasa tersebut perlu dibahas.
Ketiga, kedudukan sila kedua tersebut terkait dengan sila-sila lainnya harus
dibahas, agar makna adab yang ada dalam sila kedua itu dapat didudukkan dengan
konteks yang konsisten dan koheren dengan keseluruhan lingkup makna Pancasila
itu. Keempat, setelah makna adab dalam sila kedua dan makna setiap sila lain
diselidiki dan dikaitkan kedudukannya satu sama lain, maka narasi tafsir yang
utuh dalam Pancasila itu bisa diperoleh. Kelima, signifikansi konsep adab itu
pada akhirnya bisa ditinjau dari narasi lengkap tafsir Pancasila berdasarkan
kaitan antar sila yang sudah diperoleh itu.
Pancasila dan Islam
Tidak
seperti di era pasca-Reformasi, di mana ormas atau partai politik dapat menjadikan
Islam sebagai asas organisasi/partai, Pancasila pernah diletakkan secara
oposisional dengan Islam-sebagai-ideologi-politik di masa Orde Lama dan Orde
Baru. Pada masa pemerintahan Sukarno, hal itu terjadi terutama dalam perdebatan
di Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 yang bersidang pada 1956-1959 untuk
membuat konstitusi baru yang permanen. Konstitusi awal, UUD 1945 dengan kelima
sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaannya, pada mulanya dimaksudkan
sebagai hal yang sementara, sebagaimana dinyatakan Sukarno sendiri. [3]
Isu
yang paling panas dan lama diperdebatkan dalam Badan Konstituante adalah isu
dasar negara. Karena isu ini, partai-partai terbagi dalam tiga blok: Pancasila,
Islam, dan Sosio-Ekonomi. Blok Pancasila (53%) terdiri dari Partai Nasional
Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan partai-partai kecil lain.
Blok Islam (44%) disokong oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan partai-partai
kecil lain. Sisanya di blok Sosio-Ekonomi yang, karena terdiri dari
partai-partai kecil, tak mendominasi perdebatan.[4]
Hal
yang relevan dicatat dari perdebatan di Badan Konstituante ini adalah adanya
keleluasaan untuk mengkritik Pancasila sebagai dasar negara. Ini tidak seperti
diskursus mengenai Pancasila di era Orde Baru dan setelahnya yang didominasi
oleh puja-puji pada Pancasila sebagai suatu ideologi yang seolah tanpa cacat;
bahwa Pancasila adalah yang terbaik atau bahwa dengan Pancasila, Indonesia
menjadi “negara paripurna”. Sutan Takdir Alisjahbana dari Partai Sosialis
Indonesia (PSI) misalnya, menyatakan bahwa status Pancasila sebagai falsafah
negara adalah hal yang berlebih-lebihan, karena Pancasila itu mengandung
kontradiksi dalam dirinya, tidak memiliki kebulatan dan kesatuan logis, serta
hanya kumpulan paham yang berbeda untuk menenteramkan semua golongan pada
rapat-rapat.[5]
Menariknya, PSI berada di blok Pancasila dan Sutan Takdir menerima Pancasila
sebagai wujud kompromi politik, meski menolak gagasannya sebagai falsafah yang
utuh dan komprehensif.
Saifuddin
Zuhri dari NU mengatakan bahwa Pancasila mengandung pertentangan-pertentangan
disebabkan tiadanya kebulatan pikiran. Perwakilan NU lain, Kiai Ahmad Zaini,
menyatakan Pancasila adalah formula kosong yang ambigu, yang karena itu tak
layak menjadi dasar negara; selain itu, Pancasila itu dapat mengakui keberadaan
penyembah batu dan pohon. Ahjak Sosrosugondo, masih dari NU, menyebut Pancasila
menoleransi ideologi anti-Tuhan, yaitu komunisme. Roeslan Abdulgani, tokoh PNI,
berupaya menangkis kritik itu dengan mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah
sintesis dari gagasan-gagasan Islam modern, Marxisme, dan demokrasi asli
seperti dijumpai di desa-desa dan dalam komunalisme penduduk. Arnold Mononutu
(PNI, Kristen), menyatakan bahwa Pancasila bersifat religius-monistis, yang
dapat dia terima sebagai orang Kristen untuk dijadikan Dasar Negara Republik
Indonesia.[6]
Pandangan
yang terakhir memicu respons dari Saifuddin Zuhri (NU) ketika menyatakan bahwa
konsep monoteisme di sila pertama kabur maknanya dan dapat ditafsirkan oleh
tiap kelompok agama sesuai keinginan mereka sendiri. Mohammad Natsir,
perwakilan Masyumi, menyebut pandangan Arnold Mononutu itu sebagai tragedi
netralitas Pancasila, yang ternyata terbuka terhadap berbagai penafsiran
relatif. Menurut Natsir, kalaulah ia memilih satu warna, salah satu ideologi,
ia akan bercorak, ia tak akan netral lagi; raison d’etre-nya tak ada
lagi; ia bukan Pancasila lagi. Menguatkan pandangan dari NU, Natsir juga
menyebut Pancasila mengandung makna yang kabur. Lebih dari sekadar kabur, bagi
Natsir, Pancasila adalah konsep sekuler “lā dīniyyah”, dalam pengertian
bahwa ia tidak diderivasi dari wahyu Tuhan, tetapi dari paham-paham sekuler.[7]
Perwakilan
Masyumi lain, Isa Anshary, menyatakan bahwa Pancasila tak memiliki makna yang
jelas dan baginya, Islam lebih jelas dan berdasar pada wahyu Tuhan, sehingga
Islam lebih baik sebagai dasar negara. Tahir Abubakar dari Partai Syarikat
Islam Indonesia (PSII) menyebut Pancasila versi UUD 1945 bukan merupakan
konsensus politik nasional karena “tujuh kata” di Piagam Jakarta dihapus, satu
hal yang turut dikuatkan Kahar Muzakkir dari Masyumi dan disebutnya sebagai
intrik politik kaum nasionalis sekuler. Ringkasnya, kelompok Islam secara umum
berupaya mengetengahkan kelemahan-kelemahan Pancasila sembari menunjukkan bahwa
Islam lebih jelas dan komprehensif sebagai dasar negara.[8]
Persoalan
dasar negara ini membuat Konstituante tak mampu mencapai keputusan yang memenuhi
kuorum setelah hampir empat tahun bersidang. Geram dengan perdebatan yang tak
usai ini, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akhirnya Sukarno membubarkan
Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi dan
bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD ’45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan
dengan konstitusi. Ambiguitas makna “menjiwai” dan “satu rangkaian kesatuan”
ini di kemudian hari masih mempengaruhi dis-kursus hubungan Islam-Pancasila
dalam tata perundang-undangan dan sempat terangkat dalam upaya reformasi
konstitusi pasca-Orde Baru.[9]
Pada
masa Orde Baru, rezim Suharto menggalakkan penerapan Pancasila secara murni dan
konsekuen, sehingga menjadi ideologi yang eksklusif. Untuk pertama kali,
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum disebut eksplisit, yakni
melalui TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. TAP MPRS ini juga mengunci Pancasila
dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 (yang memuat Pancasila) tidak dapat
diubah oleh siapa pun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, karena mengubah
isi Pembukaan berarti pembubaran Negara. Pada masa ini, Pancasila merembesi
hampir segala lini kehidupan, dari demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila,
hingga moral Pancasila, masyarakat Pancasila, bahkan manusia Pancasila.[10]
Pada
masa Orde Baru, setidaknya tiga hal relevan disebut dalam hubungannya dengan
organisasi/partai, khususnya organisasi/partai Islam. Pertama, dengan
justifikasi untuk mengeliminasi antagonisme antar golongan akibat banyaknya
partai, rezim merestrukturisasi partai-partai politik menjadi dua partai dan
satu Golongan Karya. Semua partai Islam (NU, PSII, Perti, dan Parmusi) berfusi
ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kebijakan ini dipicu, antara lain,
oleh perwakilan partai-partai Islam yang mengangkat kembali isu Piagam Jakarta
pada Sidang Umum MPRS 1968.[11]
Kedua,
melalui TAP Nomor II/MPR/1978, MPR mengeluarkan ketetapan mengenai Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa. TAP MPR
ini menyatakan bahwa P4 tidak dimaksudkan untuk menafsirkan Pancasila sebagai
dasar negara, tetapi ditujukan untuk menjadi penuntun dan pegangan hidup dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia dan
dilaksanakan secara bulat dan utuh. Jika dibandingkan dengan Pidato Sukarno 1
Juni 1945 yang berisi pemikiran filsafat-politik, P4 lebih tampak seperti
pedoman moral, moral Pancasila. P4 lalu diwajibkan untuk pegawai negeri dan
Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa-siswi
di sekolah.[12]
Respons
politik Islam, yang direpresentasikan melalui PPP di parlemen, cenderung
negatif terhadap kebijakan P4 ini. Dalam Sidang Umum MPR 1978 untuk mengesahkan
P4 dan melegalisasi aliran kepercayaan, fraksi PPP walk out, dipimpin oleh Rais
Syuriah NU KH Bisyri Syansuri. Di antara argumen PPP waktu itu adalah bahwa MPR
tidak punya hak untuk mengatur individu, sebagaimana tercermin dalam kebijakan
P4, karena moral seharusnya diserahkan pada agama. Argumen PPP melawan
penerapan PMP di sekolah ialah karena melihat detail buku-buku PMP yang,
menurut PPP, antara lain telah menyatakan bahwa semua agama sama sakralnya dan
mengafirmasi acara doa bersama lintas agama. Terlebih, menurut mereka, P4 dan
PMP telah membuat Pancasila menjadi semacam agama. Tokoh-tokoh Muslim yang
mendukung keberatan PPP ini antara lain Mohammad Natsir, Sjafruddin
Prawiranegara, dan AM Fatwa.[13]
Ketiga,
rezim Orde Baru mengumumkan dan kemudian menetapkan Pancasila sebagai asas
tunggal bagi semua partai politik dan ormas dengan tujuan menjaga kohesivitas
politik. Dengan terbitnya UU Parpol dan Ormas ini, PPP dan ormas-ormas Islam
menghadapi pilihan sulit: berkompromi dengan mengubah asas organisasi atau
dibubarkan. Pada akhirnya, PPP dan sebagian besar ormas Islam memprioritaskan
kelangsungan hidup partai/organisasi. Ormas Islam yang menolak ialah Pelajar
Islam Indonesia (PII) yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah pada 1987.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pecah menjadi dua: HMI Diponegoro yang menerima
Pancasila dan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi (HMI MPO) yang bersikukuh
dengan asas Islam.[14]
Penolakan
kebijakan asas tunggal datang dari tokoh berpengaruh seperti Deliar Noer dan
Sjafruddin Prawiranegara yang menyatakan bahwa Pancasila tidak pernah
dimaksudkan oleh para pendiri bangsa sebagai asas untuk seluruh organisasi,
tetapi sebagai dasar negara. AM Fatwa dalam satu khotbahnya menyeru umat Islam
untuk mempertahankan asas Islam hingga titik darah terakhir. Pada 1980, muncul
Petisi 50, yang terdiri dari 50 politisi kenamaan, termasuk di dalamnya Natsir,
dan jenderal-jenderal pensiun, termasuk di dalamnya AH Nasution, yang
mengeluarkan kecaman terhadap Orde Baru yang menganggap serangan terhadap
dirinya sebagai serangan terhadap Pancasila. Prawiranegara secara khusus
menulis surat panjang bertajuk Pancasila sebagai Azas Tunggal pada 1983 dan
menyampaikannya pada Presiden Suharto dan mengirimkannya ke para pemimpin
lembaga-lembaga tinggi negara. Dalam surat itu, ia menyatakan antara lain bahwa
mendirikan organisasi berasas Islam ialah bagian dari kebebasan beragama umat
Islam dan melarang hal ini berarti sama dengan melanggar UUD 1945 dan, dengan
demikian, bertentangan dengan Pancasila sendiri.[15]
Politik
asas tunggal ini turut memicu terjadinya kekerasan, seperti yang terjadi dalam
peristiwa Tanjung Priok 1984, di musala tempat sering diadakan khotbah yang
menentang asas tunggal itu, dengan korban 400 orang. Peristiwa besar lain
adalah tragedi Talangsari 1989 di Lampung dengan 246 korban tewas. Poin minimal
yang dapat ditarik dari peristiwa-peristiwa di masa Orde Baru ini sederhana
saja: kemultitafsiran atau maleabilitas Pancasila, yang amat dipengaruhi oleh
konstelasi politik di masanya, mengandung potensi untuk ditarik sedemikian rupa
sehingga ia dapat menjadi alat pemukul oposisi politik atau mereka yang
dianggap subversif.[16]
Pancasila dan Marxisme / Komunisme
Bila Orde Baru melarang komunisme /
Marxisme-Leninisme dan menyatakannya bertentangan dengan Pancasila melalui TAP
Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU Ormas 8/1985, tidak demikian dengan Orde Lama. Orang
yang sering dilabeli sebagai “penggali” Pancasila, Sukarno, sangat terpengaruh
gagasan Marxisme dan, hingga taraf tertentu, juga Leninisme. Pada 1926, Sukarno
menulis artikel panjang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dalam
artikel itu, ia berargumen bahwa tiga kekuatan politik terbesar ini bisa dan
harus bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melawan imperialisme. Bila
Orde Baru beralasan bahwa Marxisme bertentangan dengan Pancasila karena
Marxisme adalah paham anti-agama, Sukarno dalam tulisan itu menyatakan bahwa
kaum Islamis harus bekerja sama dengan kaum nasionalis dan Marxis – dalam dis-kursus
waktu itu, Islamis merujuk pada Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin
al-Afghani dan Muhammad Abduh.[17]
Sukarno dalam tulisan itu juga
mengajukan argumen tentang kompatibilitas Islam dan Marxisme. Mengikuti
pandangan gurunya, HOS Tjokroaminoto yang menulis buku Islam dan Sosialisme
(1924), Sukarno menyatakan bahwa konsep “nilai lebih” (meerwarde atau surplus
value) dalam kritik Karl Marx terhadap kebijakan kapitalisme adalah sama
dengan konsep riba dalam Islam. Sukarno juga menyatakan bahwa taktik permusuhan
Marxisme dengan agama adalah taktik Marxisme kuno yang harus diubah. Ia meminta
kaum Marxis untuk membedakan antara materialisme historis dan filsafat
materialisme (wijsgerijg materialism), dan meletakkan Manifesto Komunis
dalam konteks permusuhan kaum Marxis terhadap gereja-gereja di Eropa. Dalam
banyak tulisan dan pidatonya, Sukarno berkali-kali mengutip pandangan-pandangan
intelektual Marxis dan meletakkan imperialisme Belanda dalam satu paket dengan
kapitalisme. Pikiran Marxisme itu pula yang mendasari lahirnya konsep marhaen
ala Sukarno.[18]
Di masa-masa akhir pemerintahannya,
Sukarno menggagas “sosialisme ala Indonesia” dan Nasakom, persatuan tiga
kekuatan politik: nasionalis, agama, dan komunis. Sukarno merujuk sila kelima
(keadilan sosial) ke konsep Marxis mengenai eksploitasi. Dengan tampak semakin
gandrungnya Sukarno akan gagasan-gagasan Marxis, hampir mustahil ia akan
mengatakan, seperti Orde Baru, bahwa Marxisme / Komunisme, sekurang-kurangnya
sebagai ideologi dan bukan partai politik yang menginduk ke Communist
Internasional (Comintern), adalah bertentangan dengan Pancasila. Di atas
segalanya, menurut Sukarno, perumusan Pancasila itu sendiri, hingga taraf
tertentu, terinspirasi oleh gagasan Marxis.[19]
Pancasila dan Liberalisme /
Kapitalisme serta Demokrasi
Bagaimana Pancasila semestinya
diterjemahkan ke dalam tata negara tidak selalu sama antar-periode
pemerintahan. Dengan premis bahwa spirit Pancasila yang sila-silanya sudah
tercantum dalam Pembukaan UUD merembesi batang tubuh UUD, fakta bahwa terjadi
reformasi konstitusi pada masa Reformasi itu sudah mengonfirmasi bahwa sistem
pemerintahan ala Pancasila mengandung tafsir yang tak tunggal. Sila yang secara
khusus berkaitan dengan sistem pemerintahan ialah sila keempat (kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan).
Sistem pemerintahan dalam kerangkan
Pancasila tidak menjadi dis-kursus dominan di awal Orde Lama. Sepuluh tahun
pertama pasca-proklamasi kemerdekaan bahkan Pancasila hampir terlupakan. Di
masa Revolusi (1945-1949), pemerintah Republik disibukkan oleh perjuangan
melawan Belanda yang mencoba kembali selepas Jepang pergi sembari meredam
insurgensi dari dalam, seperti beberapa daerah yang tak ingin masuk dalam
Republik (salah satu yang signifikan adalah Republik Maluku Selatan), pemberontakan
Darul Islam, dan Peristiwa Madiun 1948. Periode 1950-1959, dengan dasar
konstitusi berupa Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, merupakan periode
demokrasi parlementer, atau sering juga disebut demokrasi liberal, demokrasi
yang tidak sama dengan yang diimajinasikan Sukarno melalui pemerintahan dengan
“musyawarah mufakat”. Sengitnya persaingan partai-partai memunculkan perpecahan
antar-golongan dan kabinet yang jatuh-bangun.[20]
Didukung
oleh elemen-elemen yang lelah dengan partai-partai yang berselisih di
Konstituante dan tak juga mencapai mufakat dalam isu dasar negara, upaya untuk
menerapkan demokrasi ala Pancasila mulai muncul di UGM, Yogyakarta, pada
Februari 1959, dalam seminar yang diisi Sukarno dan tokoh-tokoh penting lain
seperti Yamin, Ruslan Abdulgani, Notonagoro, dan Drijakara dengan tajuk Pantjasila
Menundjukkan Demokrasi Terpimpin. Puncaknya ialah Dekrit Presiden 5 Juli
1959 tentang pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Inilah permulaan
era Demokrasi Terpimpin. Menjelaskan motif di balik Dekrit itu, dalam pidatonya
pada 17 Agustus 1959, Sukarno menyatakan bahwa dasar revolusi yang ada saat itu
tidak keruan mana letaknya, oleh karena masing-masing partai menaruhkan
dasarnya sendiri, sehingga dasar Pancasila pun sudah ada yang meninggalkan,
diganti dengan politik liberal, diganti dengan ekonomi liberal. Ia juga
mengatakan bahwa UUDS 1950 menekan jiwa revolusi, menghambat-mengendurkan
jalannya revolusi dan Konstituante ternyata tak mampu menjadi penyelamat
revolusi. Maka, lanjutnya, sistem liberalisme harus dibuang jauh-jauh,
demokrasi terpimpin harus ditempatkan sebagai gantinya.[21]
Menurut
Sukarno, Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarki
liberalisme, tanpa autokrasi diktator. Ia mengimajinasikan demokrasi ala Indonesia
seperti demokrasi di desa-desa di mana keputusan-keputusan menyangkut manajemen
desa dimusyawarahkan dan diputuskan oleh para sesepuh desa. Pidato itu kemudian
menjadi “Manifesto Politik” (Manipol), dan setahun kemudian ditambah dengan
USDEK (UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi
Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Manipol-USDEK kemudian menjadi
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN bersama beberapa dokumen lain
dimasukkan ke dalam Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, buku
indoktrinasi yang diwajibkan sebagai buku daras untuk seluruh mahasiswa di
universitas-universitas.[22]
Dalam
ranah praksis, Manipol-USDEK mengubah sistem pemerintah dalam tiga hal.
Pertama, demokrasi parlementer menjadi presidensial dan dengan demikian,
meningkatkan kekuatan eksekutif (presiden). Kedua, dibentuklah lima lembaga
baru dan/atau lembaga yang direstrukturisasi yang membentuk MPRS, yakni Dewan
Menteri Kabinet Karya, Dewan Nasional (DN), Dewan Perancang Nasional (DPN),
Front Nasional Baru (FNB), dan Parlemen Baru (restrukturisasi dari DPR, menjadi
DPR Gotong Royong). Ketiga, dibentuknya Golongan Karya (Golkar, golongan
berbasis massa sipil dari beragam profesi. Golkar mengisi DN, DPN, FNB, dan
setengah dari Parlemen. Sesuai Manipol, sebagian besar orang-orang yang dipilih
untuk mengisi lembaga-lembaga itu harus melalui persetujuan Presiden. Keputusan
diraih melalui musyawarah-mufakat dan jika mufakat tak tercapai, keputusan
akhir diserahkan pada Presiden.[23]
Dengan
demikian, Manipol-USDEK telah memberikan kekuatan politik yang besar dan
terpusat pada diri Presiden, apalagi setelah keluar TAP MPRS Nomor
III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno
Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Pada kenyataannya, dengan
alasan suasana revolusi, pemerintahan Sukarno sangat membatasi pers dan
mewajibkan pada pegawai negeri, pemimpin partai, dan redaktur surat kabar
menandatangani pernyataan kesetiaan pada Manipol-USDEK.[24]
Tak
kalah mencolok dan kontroversial adalah pembubaran Masyumi dan PSI karena rezim
menganggap keduanya terlibat dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI). Kedua partai itu dibubarkan dengan dasar Penetapan
Presiden 7/1960 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian yang
menyatakan bahwa, agar suatu organisasi dapat diakui sebagai partai, ia harus
tegas mencantumkan dalam anggaran dasarnya bahwa ia menerima UUD serta
mendasarkan program kerjanya atas Manifesto Politik 17 Agustus 1959 yang telah
dinyatakan menjadi haluan Negara. Penetapan Presiden ini mengatur bahwa
Presiden dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang bertentangan atau
memiliki program yang bermaksud merombak asas dan tujuan negara, juga partai
yang pemimpinnya turut serta dalam usaha pemberontakan sementara partai itu
secara resmi tidak menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu.[25]
Dengan
tujuan untuk mengamankan kehidupan bangsa dan negara yang sedang berevolusi
membentuk masyarakat Sosialis Indonesia, muncul Penetapan Presiden Nomor 11
Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pasal pertama dari PNPS
11/1963 ini memidana siapa pun yang dianggap memutarbalikkan, merongrong, atau
menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara. Ringkasnya,
Demokrasi Terpimpin adalah otoritarianisme atas nama Pancasila. Menjelang
pertengahan dekade, Sukarno berubah haluan, dari Manipol-USDK yang menekankan
Golkar menjadi Nasakom. Karena itu, PKI makin menguat dan menjadi pemain
dominan dalam kontestasi politik, sementara di sisi lain, kelompok militer yang
berada dalam Golkar merasa ditinggalkan. Ini satu hal yang memicu permusuhan
militer dengan PKI, yang nantinya akan berujung pada Peristiwa 1965 dan
runtuhnya rezim Sukarno.[26]
Rezim
selanjutnya, Orde Baru, membangun legitimasinya di atas premis bahwa komunisme
bertentangan dengan Pancasila. Pada 1974, dalam pidatonya di acara Dies Natalis
UGM ke-25, Suharto mengutarakan perlunya ada kesatuan tafsir mengenai Pancasila
agar dapat menghindari penggunaan yang salah dari Pancasila, hanya sebagai
cantolan untuk kepentingan ideologi golongan seperti dalam masa Nasakom di
zaman Orde Lama, zaman yang menurutnya bangsa terkotak-kotak dalam kesempitan
paham atau ideologi golongan. Rezim Suharto menamai demokrasinya “Demokrasi
Pancasila”, yang pada ranah praktisnya sebagian diilhami oleh Demokrasi
Terpimpin era Sukarno, yakni memperkuat Golkar sembari memperkecil peran partai
politik dengan mengarahkannya agar lebih berorientasi pada program alih-alih
ideologi. Seperti tampak dalam banyak retorika politik Orde Baru, Demokrasi
Pancasila bagi Orde Baru adalah demokrasi yang mementingkan harmoni dan
stabilitas politik daripada kegaduhan akibat pertengkaran ideologi.[27]
Seperti
sudah disebutkan, pada 1973 Orde Baru memaksa partai-partai politik untuk fusi
dan memilih satu dari dua partai saja: PPP atau PDI. Pada 1975, Orde Baru
meluncurkan kebijakan “masa mengambang” yang membatasi struktur partai hingga
tingkat kabupaten, tidak boleh rendah dari itu. Di sisi lain, Golkar yang saat
itu disebut Organisasi Peserta Pemilu (OPP), memiliki struktur hingga tingkat
desa/kelurahan. Pegawai negeri sipil diwajibkan memilih Golkar. Bila Golkar di
era Orde Lama aktif secara politik melalui demonstrasi dan pengerahan massa,
Golkar Orde Baru menjadi mesin elektoral rezim. Demokrasi Pancasila ala Orde
Baru secara de facto bersistem politik satu partai. Kekuatan politik terpusat
pada Suharto. Tanpa harus melalui persetujuan legislatif, ia bisa memecat
anggota kabinet dan pejabat militer. Ia juga memiliki kuasa untuk menyeleksi
anggota DPR melalui Komite Pemilu di bawah Departemen Dalam Negeri. Meskipun mengambil
ekonomi kapitalis, dengan membuka keran investasi asing, secara politik, Orde
Baru tetaplah sebuah rezim autokrasi.[28]
Alasan
penerapan UUD 1945 yang menjadi turunan Pancasila menghasilkan dua rezim
autokrasi adalah bahwa UUD 1945 mengandung otoritarianisme yang inheren di
dalamnya, yang ditandai dengan pemberian kekuasaan yang berat ke eksekutif,
tidak jelasnya sistem checks and balances, terlalu banyak hal diserahkan
pada aturan di tingkat bawah konstitusi, adanya pasal-pasal ambigu, terlalu bergantung
pada integritas dan kehendak baik politik, adanya persoalan yang mengalami
kekosongan hukum, dan adanya Penjelasan setelah Batang Tubuh. Tampak bahwa
Pancasila, khususnya sila keempat, dapat menjustifikasi otoritarianisme. Frasa
“dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” dipahami oleh dua rezim itu sebagai
pembeda dari demokrasi liberal dan, pada gilirannya, justru melapangkan jalan
bagi upaya pemusatan politik di tangan presiden.[29]
Pancasila Pasca-Reformasi
Pada
tahun-tahun awal pasca-Reformasi, Pancasila tak banyak bergaung dalam dis-kursus
politik, antara lain karena publik masih mengasosiasikannya dengan Orde Baru.
Namun, ada perkembangan yang relevan dicatat. Di era awal Reformasi, MPR
mengeluarkan TAP Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR II/1978
tentang P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Dengan TAP MPR ini, P4 tak lagi berlaku dan Pancasila ditegaskan posisinya
sebagai dasar negara. Selain itu, amandemen Konstitusi 1999-2002, meski masih
mengundang kritik terhadap beberapa kelemahannya, telah berhasil mempertahankan
Pembukaan UUD 1945 sebagaimana asalnya dan menghalau aspirasi untuk
mengembalikan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Konstitusi yang baru hasil
amandemen lebih demokratis; memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih jelas
antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; dan telah memperkuat jaminan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).[30]
Di
luar reformasi Konstitusi, Pancasila cenderung terlupakan dalam wacana publik.
Pancasila baru menggema lagi di pertengahan dasawarsa 2000-2010. Yang berbeda
dari masa Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila yang digemakan di era
pasca-Reformasi ini muncul mula-mula dari bawah, dari masyarakat sipil, khususnya
dari elemen yang sebelumnya sangat kritis terhadap Orde Baru. Upaya “restorasi”
Pancasila ini muncul terutama karena Reformasi telah membuka kran kebebasan
berpendapat dan desentralisasi sehingga memberi jalan lapang bagi gerakan Islamis
(dalam pengertian yang menghendaki formal-isasi hukum Islam dan, bagi sebagian,
menginginkan Indonesia menjadi negara Islam) untuk naik ke permukaan dis-kursus
politik. Gerakan Islamis ini tentu mengandung variasi dalam spektrum, dari yang
kadang menempuh jalur kekerasan hingga yang bergerak di jalur konstitusional,
dari yang model Majelis Mujahidin dan HTI, perjuangan “NKRI bersyariah” ala
Front Pembela Islam, gerakan-gerakan pembasmian aliran sesat, aspirasi Islam
melalui prosedur demokrasi, hingga munculnya perda-perda syariah di tingkat
lokal, yang didukung berbagai partai politik, tak terbatas partai-partai Islam.[31]
Sebagaimana
pola sejak awal kemerdekaan, di mana selalu ada kompromi dan kontestasi antara
golongan kebangsaan dan golongan Islam, demikian pula kasus pasca-Reformasi.
Penolakan aspirasi pengembalian Piagam Jakarta dalam proses amandemen
Konstitusi memicu koneksi berupa aspirasi keislaman dalam aturan-aturan di
tingkat yang lebih renda, seperti UU Sisdiknas 2003 dan UU Anti-Pornografi dan
Porno-aksi (APP). Pada saat yang bersamaan, setelah tak berhasil dilakukan dari
atas, islamisasi gencar bergerak dari bawah. Tahun 2005 menjadi tahun penting
dalam sejarah aspirasi Islamis pasca-Reformasi. Pada tahun ini MUI mengeluarkan
fatwa yang mengharamkan pluralisme, sekularisme, dan liberalisme; fatwa
keharaman doa bersama lintas agama; fatwa keharaman pernikahan beda agama; dan
fatwa kesesatan Ahmadiyah. Aspirasi Islamis ini mengalami peningkatan pada
tahun-tahun berikutnya, sekalipun kombinasi kekuatan partai-partai Islam atau
berbasis massa Islam belum mampu hingga kini mengalahkan dominasi partai-partai
sekuler dalam politik elektoral.[32]
Menguatnya
aspirasi Islamis di satu sisi memicu reaksi dari sisi yang lain. Di antara yang
layak dicatat ialah dis-kursus pada 2006, bertepatan dengan masih panasnya
perdebatan mengenai RUU APP. Pada peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006,
pertemuan besar di Jakarta yang dihadiri ratusan orang bersama Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), para menteri, dan tokoh-tokoh berpengaruh dari
berbagai kalangan mendeklarasikan Maklumat Keindonesiaan, yang antara lain
menegaskan Pancasila sebagai suatu hal yang telah digali, dilahirkan, dan
disepakati oleh para pendiri republik dan tumbuh dari benturan kepentingan,
sumbang-menyumbang gagasan.[33]
Selepas
pembacaan maklumat itu, Presiden SBY memberikan pidato dengan tajuk Menata
Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila. Dalam pidato itu,
Presiden menegaskan Pancasila sebagai falsafah, dasar negara, dan ideologi
terbuka, open ideology, living ideology, bukan dogma yang statis
dan menakutkan. Namun demikian, Presiden memberikan identifikasi terhadap
ideologi-ideologi yang menjadi tantangan Pancasila, dan dalam pidato itu
Presiden menyebut kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan sosialisme sebagai
sesuatu yang tidak sesuai jiwa dan semangat Pancasila. Bagian ini tampak
paradoks, karena mempertentangkan Pancasila dengan ideologi lain sementara
sebelumnya disebut bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka.[34]
Dalam
dis-kursus pasca-Reformasi, Pancasila kerap disebut sebagai konsensus nasional
dan ideologi terbuka. Bila di masa Orde Lama, Pancasila diadvokasi oleh
golongan kebangsaan, banyak pihak di era pasca-Reformasi menjadikan Pancasila
sebagai simbol pengawal kebinekaan. Namun, dis-kursus mengenai Pancasila
pasca-Reformasi tidak berhenti di situ dan tak sesederhana itu. Kalangan
Islam(is) pun berupaya untuk merebut tafsir Pancasila. Dalam sejarah Pancasila,
agaknya baru di pasca-Reformasi inilah kalangan Islam(is) berupaya mengapropriasi
Pancasila. Tentang ini, setidaknya tiga contoh signifikan layak dicatat.
Pertama,
dari kalangan pejabat tinggi. Dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo (2006),
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa Pancasila sering hanya dijadikan
tameng untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya, ia
mencontohkan, seseorang yang tidak suka dengan syariat lalu berlindung di balik
Pancasila. Waktu itu, suasana politik sedang panas oleh debat mengenai RUU APP,
sementara sebagian dari para penolak RUU APP menyuarakan Pancasila. Mengenai
hal itu, Ketua MPR dalam wawancara itu mengutarakan bahwa RUU APP tidak untuk
menciptakan disintegrasi, karena kalau dirunut pasal menimbang dan mengingat,
dia justru dalam rangka melaksanakan Pancasila juga. Jadi, tampak di sini bahwa
penentang maupun pendukung RUU APP sama-sama berupaya menggantungkan legitimasi
aspirasinya pada Pancasila.[35]
Kedua,
dari kalangan pemimpin agama. Tak lama seusai deklarasi Maklumat Keindonesiaan
itu, Ketua MUI waktu itu, KH Ma’ruf Amin, menulis kolom di Republika dengan
judul “Mencegah Upaya Sekularisasi Pancasila”. Sebagaimana sudah tampak dari
judulnya, tulisan ini ingin menekankan pentingnya unsur agama dalam Pancasila.
Dalam tulisan itu, Kiai Ma’ruf memandang Maklumat sebagai upaya membenturkan
“hak umat Islam menjalankan syariat agamanya” dengan Pancasila dan UUD 1945.
Tulisan itu juga menekankan bahwa “Pancasila bukanlah ideologi negara,
melainkan visi negara ... visi itu kemudian dituangkan dalam UUD 1945, pasal
29, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya,
para pendiri negara ini justru ingin menegaskan bahwa negara yang dibangunnya
itu bukanlah negara sekuler.” Dalam hubungan antara Pancasila dan Islam,
tulisan itu menyatakan: “Sebagai ide terbuka, sebagaimana disampaikan Presiden
SBY, seharusnya kontribusi agama, sebut saja Islam, dalam membimbing visi yang
dicita-citakan itu tidak boleh dibendung, apalagi dengan membenturkan
keduanya.”[36]
Ketiga,
dari penulis Muslim berpengaruh. Di berbagai media, Adian Husaini, penulis buku
Pancasila untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam (2010), kerap mengkritik
pandangan yang meletakkan Pancasila dalam perspektif sekuler sembari menekankan
bahwa makna sila pertama adalah tauhid. Di antara contoh tafsir Pancasila yang
sekuler yang dikutip Ali Murtopo, mantan asisten khusus Suharto, yang menyatakan
bahwa sila pertama mengandung makna hak untuk pindah agama. Husaini kerap
menekankan bahwa sila pertama tak bisa dilepaskan dari Piagam Jakarta. Mengutip
saksi sejarah pencoretan “tujuh kata”, Kasman Singodimedjo, Husaini menulis,
“Bung Hatta yang aktif melobi tokoh-tokoh Islam agar rela menerima pencoretan
tujuh kata itu menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah, tidak lain
kecuali Allah.” Mengutip saksi sejarah lain, yakni Ki Bagus Hadikusumo, ketua
Muhammadiyah waktu itu, Husaini menulis bahwa Ki Bagus bersedia menerima
penghapusan tujuh kata itu “setelah diyakinkan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha
Esa adalah tauhid.” Husaini melanjutkan, “Itu juga dibenarkan oleh Teuku
Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Hatta untuk melunakkan
hati Ki Bagus.”[37]
Makna
sila pertama memang ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak, bergantung
falsafah hidup masing-masing. Dalam tulisan berjudul Tuhan Hanya Esa, Itulah
Keyakinanku, Sukarno menyebut dirinya sebagai panteis-monoteis, dan ini juga ia
tegaskan saat menerima doktor kehormatan dalam Filsafat Tauhid dari Universitas
Muhammadiyah Jakarta pada 1965. Namun, pada periode Orde Baru, khususnya di era
penerapan asas tunggal, untuk meningkatkan keberterimaan Pancasila terhadap
organisasi-organisasi Islam, Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara
menyatakan bahwa sila pertama itu terinspirasi dari tauhid. Ia juga menyatakan
bahwa pencoretan tujuh kata merupakan hadiah umat Islam kepada bangsa Indonesia
demi menjaga persatuan.[38]
Ahmad
Syafii Maarif bahkan menulis bahwa “setiap usaha dari mana pun yang mencoba
memisahkan Pancasila dari intervensi wahyu adalah ahistoris, sebab Pancasila
yang dirumuskan pada 18 Agustus 1945 itu tidak sama dengan formula Pancasila
yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945.” Lebih eksplisit lagi, Maarif
menyatakan bahwa “sila pertama jelas sekali menunjukkan bahwa konsep Ketuhanan
dalam Pancasila bukanlah semata fenomena sosiologis, melainkan refleksi dari
ajaran tauhid”. Aksentualisasi terhadap Ketuhanan dalam sila pertama itu
memiliki satu signifikansi tafsir tersendiri. Hatta berpandangan bahwa, dengan
menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama, negara memiliki
“landasan moral yang kukuh” dan di bawah bimbingan sila pertama itu, “kelima
sila itu ikat-mengikat”.[39]
Tampak
dalam dis-kursus ini bahwa tafsir Pancasila dapat diapropriasi kelompok
Islam(is), yang disokong dengan argumen yang menekankan pada makna sila pertama
yang, dengan mengutip pandangan-pandangan dari sebagian tokoh generasi awal,
merupakan manifestasi dari tauhid. Lebih dari sekadar dis-kursus, apropriasi
terhadap tafsir Pancasila juga terjadi dalam proses uji materi (judicial
review) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009-2010 terhadap UU Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PPPA), yang diajukan oleh aktivitas
kebebasan beragama, yang sebagian darinya juga kerap mengampanyekan Pancasila
sebagai simbol kebinekaan di satu sisi dan untuk mengadvokasi hak beragama kelompok
minoritas di sisi lain. Proses uji materi ini berakhir dengan ditolaknya
tuntutan para pemohon untuk membatalkan UU PPPA.[40]
Jadi,
bila diringkas, Pancasila di era pasca-Reformasi telah mengalami tarik-ulur
diskursif. Setelah tak banyak dibicarakan di tahun-tahun awal, Pancasila
mengalami restorasi sebagai simbol kebinekaan yang dikerek untuk membendung
aspirasi Islam(is). Beberapa tahun berikutnya, Pancasila berusaha diapropriasi
oleh kelompok Islam(is) untuk menghalau penafsiran terhadap Pancasila yang
diletakkan dalam kerangka sekuler-liberal.[41]
Uraian
terhadap sejumlah isu di atas menuju pada satu kesimpulan, yaitu tentang
kemultitafsiran Pancasila; bahwa Pancasila dalam dirinya mengandung potensi
untuk mengalami tarik-ulur interpretasi oleh berbagai golongan dari sisi-sisi
yang berseberangan dalam suatu spektrum politik. Uraian di atas juga telah
menunjukkan bahwa diskursus penafsiran terhadap Pancasila pada satu periode tak
bisa dilepaskan dari konstelasi politik pada periode itu. Setelah dimasukkan
dalam Pembukaan UUD 1945 di awal kemerdekaan, Pancasila sempat dilupakan di era
Revolusi saat Republik disibukkan oleh upaya mengatasi kembalinya Belanda dan
pemberontakan-pemberontakan dari dalam. Pada 1950-1955, dengan UUDS 1950,
Pancasila juga masih tak menjadi perbincangan dominan seiring politik
pemerintahan yang dikelola dengan sistem demokrasi parlementer-liberal. Dalam
debat Konstituante 1956-1959, Pancasila dihadapkan dengan Islam dalam
persaingan menjadi dasar negara. Pancasila mulai efektif lagi sebagai dasar
negara setelah dibubarkannya Konstituante melalui Dekrit 5 Juli 1959.
Pada
1959-1965, Pancasila menjadi dasar diterapkannya Demokrasi Terpimpin dengan
kekuasaan terpusat pada diri Presiden. Dengan kata lain, Pancasila menjadi
justifikasi bagi otoritarianisme. Rezim berikutnya, mewarisi sebagian
penafsiran Pancasila ala Demokrasi Terpimpin dan menamai demokrasinya
“Demokrasi Pancasila”, dengan kekuasaan yang terpusat pada Suharto dan Golkar
menjadi mesin politik. Pada Orde Baru, Pancasila merembesi hampir segala lini,
dari demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, moral Pancasila, hingga manusia
Pancasila. Orde Baru juga menggunakan Pancasila sebagai instrumen untuk menekan
oposisi. Selepas tumbangnya Orde Baru, Pancasila sempat dilupakan di
tahun-tahun awal pasca-Reformasi. Mulai 2005, sebagai reaksi terhadap
meningkatnya aspirasi politik Islamis, Pancasila mengalami restorasi, dikerek
sebagai simbol penjaga kebinekaan. Namun, Pancasila juga mengalami apropriasi
oleh kaum Islamis. Hingga tahun 2017, Pancasila untuk pertama kalinya sejak
Reformasi menjadi instrumen legal untuk membubarkan organisasi.
Dalam
konstelasi politik yang berubah-ubah itu, Pancasila mendapat penafsiran yang
beragam, Di satu periode, Pancasila kental bernuansa sosialis dan terinspirasi
hingga tingkat tertentu oleh Marxisme. Di periode berikutnya, komunisme
dinyatakan bertentangan dengan Pancasila. Di satu periode Pancasila
dipertentangkan dengan Islam. Di periode lain, Pancasila ditekankan sila pertamanya
yang dimaknai sebagai terinspirasi konsep tauhid dalam Islam. Di satu periode,
Pancasila diusung sebagai simbol perekat kebangsaan dan penjaga kebinekaan. Di
sisi lain pada periode yang sama, Pancasila dipakai untuk melegitimasi
peraturan yang membatasi kebebasan kelompok minoritas beragama.
Lebih
dari persoalan tafsir terhadap kandungan maknanya, kontestasi juga berlangsung
di ranah rujukan otoritas tafsir. Satu pihak merujuk ke Sukarno sebagai pemilik
otoritas tafsir terhadap Pancasila. Namun, Sukarno memiliki ambiguitasnya
sendiri, yakni antara pemikirannya dalam Pidato 1 Juni 1945 dengan penerapan
Pancasila oleh Sukarno melalui Demokrasi Terpimpin. Pihak lain berpandangan
bahwa Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 bukanlah kreasi
Sukarno semata, melainkan produk konsensus para pendiri bangsa antara golongan
kebangsaan dan golongan Islam, sehingga mesti ditafsirkan dalam kerangka
konsensus itu, bukan pemikiran Sukarno.
Lebih
dari persoalan otoritas tafsir, kontestasi juga berlangsung dalam apakah satu
tafsir yang tunggal dan objektif dimungkinkan untuk diraih, seperti yang dicoba
diupayakan oleh Orde Baru. Status Pancasila juga menjadi medan kontestasi:
apakah ia cukup sebagai “dasar negara”; atau, ia bisa lebih dari itu, menjadi
ideologi sehingga bisa disejajarkan dan punya potensi untuk dipertentangkan
dengan ideologi-ideologi lain seperti komunisme, kapitalisme, liberalisme,
Islamisme, dan lain-lain; atau bahkan lebih lagi dari itu, Pancasila masuk ke
kawasan personal sebagai panduan moral dan pandangan hidup tiap individu.
Maka,
seluruh pembahasan pengantar ini menegaskan suatu tesis bahwa kemultitafsiran
Pancasila seyogyanya menjadi refleksi kritis akan upaya memperlakukan Pancasila
sebagai satu “ideologi” yang memiliki tafsir tunggal yang sedemikian obyektif
sehingga ia layak menjadi alat untuk memukul rival-rival politik rezim yang
berkuasa atau membungkam setiap yang berupaya mengkritiknya. Banyak yang
mengakui bahwa Pancasila mengandung sila-sila yang mengandung nilai-nilai
“kebaikan”. Namun demikian, sifat keredaksiannya yang umum dan ambigu itu
memang membuatnya terbuka terhadap kepelbagaian tafsir, meski ini bukan hal
yang niscaya buruk. Sementara sifat multitafsir bisa menjadi nilai positif,
tapi ketika digunakan sebagai instrumen dalam level praksis di ranah hukum,
kemultitafsiran dapat mereduksi pemenuhan prinsip legal lex certa. Namun
begitu, instrumentalisasi eksklusif Pancasila seperti pada era Demokrasi
Terpimpin Orde Lama dan Demokrasi Pancasila Orde Baru tetaplah suatu
keterpelesetan yang mesti dihindari.
Dalam
pada itu, tulisan ini hendak secara bebas mengambil satu sudut pandang atau
kerangka tertentu dalam upaya melakukan interpretasi Pancasila, di antara
pelbagai kemungkinan dan ragam tafsir yang ada, dalam usahanya untuk menggali
konsep adab sebagaimana yang terdapat dalam sila kedua Pancasila itu. Dengan
demikian, dalam tulisan ini, dipandanglah bahwa kerangka penafsiran yang utuh
dan baik bisa didapatkan dengan penyelidikan akar kata dari tiap-tiap konsep pokok
yang ada di masing-masing sila, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan hubungan
antar-sila, dengan anggapan bahwa keseluruhan sila sejatinya ialah suatu
kesatuan bangunan konseptual yang bulat dan tiada dapat dipisah-pisahkan.
Selain itu, konteks historis dari sila-sila itu juga akan diulas, walaupun
tidak seluruhnya mengingat keterbatasan kesempatan, guna menunjukkan pada jalan
tafsir yang mengakar pada ruh asasinya.
Adab dan Sila Kedua
Kata
adab secara eksplisit terdapat pada sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang
adil dan beradab”. Dalam sila itu, setidaknya terdapat tiga konsep pokok yang
perlu digali, yaitu manusia, adil, dan adab. Kata adil dan adab berasal dari
bahasa Arab, “ʿadl” dan “adab”, yang diserap melalui bahasa
Melayu, “adil” dan “adab”. Sementara itu, kata manusia berasal dari bahasa
Sanskerta, “manu”, yang diserap melalui bahasa Jawa, “manungsa”
atau “menusa”. Terdapat juga pandangan bahwa kata manusia berasal dari
dua kata bahasa Arab, “man” (من) dan “ūṣiya” (أوصي).[42]
Kata
manusia dalam bahasa Indonesia berarti “makhluk yang berakal budi (mampu
menguasai makhluk lain); insan; orang”.[43]
Sementara itu, akal dimaknai sebagai “(1) daya pikir (untuk memahami sesuatu
dan sebagainya); pikiran; ingatan; (2) jalan atau cara melakukan sesuatu; daya
upaya; ikhtiar; (3) tipu daya; muslihat; kecerdikan; kelicikan; (4) kemampuan
melihat cara memahami lingkungan”.[44]
Kata budi memiliki makna “(1) alat batin yang merupakan paduan akal dan
perasaan untuk menimbang baik dan buruk; (2) tabiat; akhlak; watak; (3)
perbuatan baik; kebaikan; (4) daya upaya; ikhtiar; (5) akal (dalam arti
kecerdikan menipu atau tipu daya)”.[45]
Sementara itu, berakal dipahami sebagai “(1) mempunyai akal; (2) pandai mencari
ikhtiar; cerdik; pandai”.[46]
Sedangkan, berbudi dimaknai sebagai “(1) mempunyai budi; (2) mempunyai
kebijaksanaan; berakal; (3) berkelakuan baik; (4) murah hati; baik hati”.[47]
Sementara
itu, dalam asal-usul serapannya, kata “manu” dalam bahasa Sanskerta
secara sederhana berarti berpikir atau berakal budi. Sedangkan dalam bahasa
Jawa, kata “menusa” dapat diturunkan dari konsep “menus-menus sing
gawe dosa” atau makhluk yang berbuat dosa. Sementara dalam turunan kata
Arabnya, kata “man” berarti siapa atau suatu pihak, sedangkan “ūṣiya”
memiliki akar kata yang sama dengan kata “waṣā” atau “awṣā” yang
terkait dengan konsep wasiat, pesan, atau amanah.[48]
Hal itu sebagaimana frasa “wa waṣṣā bihā Ibrāhīmu banīhi wa Ya’qūb” (Dan
Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya, dan demikian pula Yaqub).[49]
Dengan begitu, kata “ūṣiya” berarti orang yang diberikan wasiat/amanah.
Dengan demikian, gabungan kata “man ūṣiya” dapat dimaknai sebagai pihak
atau orang yang diberikan suatu wasiat atau amanah, yang dalam konteks ini
adalah, untuk mengelola bumi.
Dengan
demikian, arti manusia dapat dielaborasikan sebagai makhluk yang memiliki akal
dan budi, yang digunakannya untuk memahami sesuatu (termasuk lingkungan
sekitar), mencari jalan atau cara melakukan sesuatu, mengakali suatu kesulitan,
menimbang baik dan buruk serta benar dan salah, mengupayakan suatu ikhtiar, dan
mewujudkan perbuatan, akhlak, serta kelakuan baik, yang di antaranya diilhami
oleh kebijaksanaan dan kemurahan hati, untuk menjalankan wasiat atau amanah
yang dipikulnya sebagai pengelola bumi – yang dalam bahasa Islam disebut sebagai
khalifah di bumi (khalīfah fil-arḍ) – sehingga menimbulkan manfaat yang
luas dan meminimalkan mudarat yang dihasilkan, yang – di sisi lain – penggunaan
akal-pikiran dan budi itu haruslah dilakukan secara hati-hati menurut suatu
ketentuan dengan pokok-pokok yang abadi, karena manusia itu sendiri memiliki
peluang atau kemungkinan untuk terjerumus dalam kesalahan, keburukan, atau kegagalan
serta penyimpangan dari wasiat atau amanahnya itu, lantaran dia memiliki
kecenderungan untuk melakukan dosa di dalam dirinya, yakni yang timbul dari
hawa nafsunya dan godaan yang dinamik sepanjang zaman, yang mendorongnya
berbuat maksiat.
Kata
adil dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “(1) sama berat; tidak berat
sebelah; tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada
kebenaran; (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang”.[50]
Kata adil menurut asal katanya bertalian dengan kata kerja bahasa Arab “ ʿadala”
yang berarti bertindak secara proporsional, bertindak dengan benar, dan
bertindak sesuai kadar menurut suatu penghakiman atau pertimbangan, seperti
pada frasa “ ʿadala ʿalayhi fi-l-qaṣiyyah”. Kata tersebut juga terkait
dengan “ ʿadila” yang berarti suatu sikap atau tindakan menolak, memantulkan,
menyimpang, atau menjauh dari sesuatu. Hal itu seperti pada frasa “bal hum
qawm taʿdilūn” (akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menolak atau
menjauh) dan “ ʿadala ʿan-i-ṭ-ṭarīq” (dia menyimpang dari jalan itu).
Kata ini juga terkait dengan konsep kembali, seperti pada frasa “ ʿadala
ilayhi” (dia kembali padanya). Selain itu, kata tersebut juga berhubungan
dengan konsep membagi sesuatu secara sama atau menurut kadar yang tepat,
seperti dalam frasa “ ʿadaltu amtiʿata l-bayt” (aku membagi
barang-barang rumah ke dalam takaran yang sama/tepat).[51]
Pembagian
takaran yang “sama” di sini tidaklah selalu berarti sama secara kuantitas,
tetapi lebih kepada ketepatan, nilai, kondisi intrinsik, kebenaran, dan
utilitas, sehingga bagian yang secara kuantitas lebih kecil, dapat memiliki
kadar yang sama berat dengan bagian yang secara kuantitas lebih besar. Hal itu
seperti pada frasa “ ʿaddala l-qassām l-anṣibāi li-l-qasmi bayna sy-syurakāi”.
Dengan begitu, penentuan adil dilakukan menurut timbangan (al-wazn) dan
kadar (al-qadr) tertentu, bukan dipukul sama rata. Adil juga bermakna
bulat, penuh, atau integral, seperti pada frasa “ ʿsyariba ḥatta ʿaddala”
(ia minum sampai menjadi penuh). Adil juga bermakna kondisi yang sulit atau
berat di antara dua hal atau dua pilihan, seperti pada frasa “ ʿādaltu bayna
amrayni ayyuhumā”. Adil dalam bentuk “taʿaddala” berarti menjadi
lurus atau tegak pada suatu posisi yang tepat (taqawwama). Dengan
begitu, “iʿtidal” atau “iʿtadal” selain bermakna menjadi benar
atau lurus, juga bisa bermakna berdiri tegak.[52]
Sementara
itu, kata “ ʿadl” sendiri bermakna “qaṣd” yang berarti “iʿtidāl”,
yaitu moderat, berada di tengah, sedang, lurus, tegak, atau langsung (makān
ʿadl bayna farīqayn); “qisṭ” yang berarti suatu kondisi berimbang
dari bagian-bagian; “sawiyyah” yang berarti persamaan; dan “istiqāmah”
yang berarti tegak lurus menetapi suatu posisi. Suatu pemberian yang adil
dikatakan sebagai pemberian yang terukur (aʿṭāhu bi-l-ʿadl). Sedangkan
orang yang “ ʿādil” adalah orang yang memiliki keadilan dalam dirinya (dzū
ʿadl), yaitu orang dengan perkataan, penilaian, pertimbangan, penghakiman,
keputusan, dan perbuatan yang lurus dalam kebenaran, yang tidak ada keraguan, kecurigaan,
dan kejahatan di dalamnya. Sikap adil dengan begitu ialah sikap yang
menyeimbangkan sesuatu agar berada pada jalur lurus yang benar, tidak terguling
seperti beban di punggung unta yang setimbang (waqaʿa l-muṣṭariʿāni ʿidlā
baʿīr).[53]
Berdasarkan
seluruh uraian tersebut, seorang yang adil dapat dielaborasikan sebagai orang
yang memiliki perkataan, pikiran, dan perbuatan yang lurus dalam kebenaran
dengan menentukan kadar dan pertimbangan yang seimbang, proporsional, dan tepat
pada tempatnya; dan jika ia berada dalam posisi untuk menghakimi, mengevaluasi,
mengambil keputusan, mengaudit, dan pelbagai kegiatan terkait lainnya, ia akan
mengambil posisi di tengah, moderat, dan sedang, sehingga senantiasa berupaya
memihak dan tegak pada kebenaran dan tidak mudah terseret arus yang
mengombang-ambingkannya pada jalan-jalan yang tidak lurus.
Kata
adab dalam bahasa Indonesia berarti “kehalusan dan kebaikan budi pekerti;
kesopanan; akhlak”. Seseorang yang beradab dimaknai sebagai seseorang yang “(1)
mempunyai adab; mempunyai budi bahasa yang baik; berlaku sopan; (2) telah maju
tingkat kehidupan lahir batinnya”.[54]
Sementara menurut asal kata serapannya, adab berkaitan dengan kata kerja bahasa
Arab “adaba” yang berarti mengundang seseorang ke dalam perjamuan (adaba
ila ṭaʿāmih). Dalam perjamuan itulah, sesuatu yang baik dihidangkan untuk
menghormati tamu (adabahu ya’dibahu bi-l-kasr idzā daʿāhu ila ṭaʿāmih). Dengan
demikian, adab itu berkaitan dengan “ta’dīb”, yaitu suatu disiplin
pikiran dan perilaku, kehalusan bahasa, kemuliaan akhlak, serta akuisisi
kualitas dan atribut-baik dalam akal dan jiwa, seperti saat menghormati tamu
dalam suatu perjamuan, yang memperlihatkan karakteristik terdidik, terpelajar, terlatih,
tertata, teratur, patuh, mengerti, sopan, dan penuh dengan kecermatan serta
kehati-hatian langkah (ta’addab). Jika disandingkan dengan kata negeri
(dan konsep komunitas, wilayah, organisasional, atau otoritas lain), seperti
pada frasa “ādaba l-bilād”, kata kerja “adaba” menjadi bermakna
memenuhi suatu negeri dengan keadilan dan kebenaran.[55]
Karena
kata kerja “adaba” dan bentuk proses “ta’dīb” itu dikaitkan
dengan suatu disiplin pikiran, maka adab berhubungan dengan aspek keilmuan (ʿilm),
ibarat (ʿibrah), atau pengetahuan (maʿrifah), yang mana semua itu
ialah yang menghindarkan diri seseorang dari segala bentuk kesalahan. Hal itu
untuk memenuhi unsur keteraturan, kepatuhan, dan sejenisnya, yang ada dalam “ta’dīb”
itu. Dengan demikian, adab dapat dikatakan sebagai sifat-diri yang melindungi
pemiliknya dari keburukan, di mana sifat-diri itu terbentuk oleh suatu proses
akuisisi keilmuan, baik melalui pengajaran, pelatihan, pendidikan, pengaturan,
dan lain-lain. Dengan begitu, adab berkaitan dengan suatu kultur pembelajaran
atau literasi yang berbudaya/berbudi luhur. Pembelajaran, ilmu, dan pengetahuan
yang sejati hanyalah yang dapat membuat seseorang menjadi beradab. Semua bentuk
keilmuan yang membuat manusia menyimpang dari kebenaran adab bukanlah ilmu
sejati. Dengan kata lain, adab dapat dianggap juga sebagai tujuan pedagogi.
Selain
itu, bentuk kata kerja “adaba” bila dikaitkan dengan entitas wilayah,
otoritas, organisasional, dan sejenisnya, diartikan sebagai perbuatan memenuhi
sesuatu dengan keadilan dan kebenaran. Dengan begitu, adab juga berkaitan
dengan suatu sikap dan etika profesional dalam mengemban suatu pekerjaan atau
tanggung jawab, dalam rangka menjaga pelaksanaan tanggung jawabnya itu secara
lurus, benar, dan berkeadilan. Sikap dan etika profesional itu tentunya timbul
dari unsur-unsur yang ada sebelumnya, yaitu disiplin pikiran dan perilaku,
kemuliaan akhlak, ilmu pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan pelatihan, dan
berbagai hal terkait yang telah disebutkan, yang semuanya bermuara pada
pembiasaan diri untuk menetapi segala hal yang menjadi karakteristik keluhuran
taraf hidup manusia. Dengan demikian, adab bukanlah sekadar sopan-santun
sebagaimana yang jamak dipahami, melainkan sesuatu yang lebih kompleks.
Untuk
menangkap gambaran utuhnya secara sederhana, adab dapat diinterpretasikan
sebagai suatu disiplin jiwa, pikiran, dan badan yang memastikan seorang manusia
mengenali dan menyikapi sesuatu dengan benar (proporsional dan pada tempatnya).
Dengan begitu, adab secara sederhana dapat diuraikan ke dalam berbagai bagian,
seperti adab kepada Tuhan, adab kepada nabi, adab kepada guru, adab kepada
orang tua, adab kepada alam, dan lain-lain. Manusia yang beradab adalah manusia
yang mampu membedakan setiap entitas tersebut dan memberikan hak yang sesuai
pada masing-masingnya, yang menjadi kewajiban yang ditanggung oleh orang
tersebut. Seseorang yang ramah dan sopan pada tetangganya tidak dapat disebut
beradab jika melakukan eksploitasi yang merusak alam (biadab pada alam).
Seseorang yang menghormati orang tuanya tidak dapat disebut beradab jika tidak
menghargai gurunya. Demikian juga seseorang yang baik pada manusia tidak dapat
disebut beradab jika ia tidak menempatkan otoritas Tuhan, nabi, dan ulama pada
tempat yang semestinya.[56]
Dari
sini, kita dapat melihat kaitan yang erat antara adab dengan ilmu dan proses
pembelajaran (termasuk pembiasaan dan pelatihan). Seseorang yang mendapatkan
pengetahuan yang parsial dan dualis, tidak akan dapat mencapai kebenaran ilmu
yang sejati. Itu karena proses berpikir dan membuat-penilaian seseorang yang
demikian akan menjadi paradoksal, penuh pertentangan dan inkonsistensi. Hal itu
seperti orang yang mengatakan, “Walaupun saya seorang pelacur atau LGBT, saya
orang yang baik secara sosial,” atau perkataan, “Walaupun saya sering berbohong,
saya pemimpin yang baik dan merakyat.” Pemikiran dualis yang paradoksal itu
pada akhirnya akan menghasilkan kerusakan-kerusakan, karena standar kebenaran
tidak lagi integral, sehingga manusia tidak lagi menjadi beradab secara utuh.
Hal itu membawa indikasi bahwa segala pemikiran, sikap, perilaku, dan perbuatan
yang benar adalah adab; dan ia berasal dari pengambilan keputusan yang tepat,
yang disebut sebagai hikmah; pengambilan keputusan yang tepat itu berakar dari
pengetahuan yang benar, yang disebut sebagai “al-ʿilm”, yang umumnya
diterjemahkan sebagai ilmu saja, yang lengkapnya ialah ilmu yang benar dan
sejati.
Dengan
demikian, dapat dinyatakan bahwa segala kerusakan yang terjadi berkaitan dengan
ulah tangan manusia, seperti kemiskinan sistemis, kerusakan alam, pemanasan
global, penyakit seks menular, ketimpangan ekonomi berlebihan, terputusnya pewarisan
demografi, rusaknya peran institusi keluarga, dan lain-lain, sejatinya berakar
pada satu titik yang sama, yaitu hilangnya adab. Hilangnya adab itu berasal
dari kebingungan dalam pengambilan sikap atau keputusan, yang berarti ketiadaan
hikmah. Ketiadaan hikmah itu berawal dari ketiadaan ilmu. Bukan berarti bahwa
ketiadaan ilmu itu sama dengan tidak majunya sains dan teknologi. Ilmu di sini
ialah ilmu sejati, suatu pengetahuan yang membuat manusia dapat mengatakan
bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Tidak semua sains
(sosial maupun natural) dan teknologi adalah ilmu yang benar dan sejati. Sains
dan teknologi itu secara inheren memiliki kandungan kebaikan dan keburukan di
dalamnya, yang harus bisa dipilah oleh manusia menggunakan hikmah yang dia
miliki. Namun, dunia pos-modern tempat manusia hidup saat ini, boleh dibilang
merupakan dunia dengan kemajuan sains, tapi miskin hikmah ilmu.[57]
Tibalah
saatnya kita harus merangkai segenap konsep pokok sila kedua ini. Berdasarkan
uraian sebelumnya, kita dapat menangkap bahwa konsep manusia, adil, dan adab
ialah saling bertalian. Seluruhnya berujung pada upaya manusia untuk
menjalankan wasiat perannya secara lurus, baik, dan benar, sehingga maujudlah
kehidupan yang beradab; yang mana, ikhtiar yang lurus, baik, dan benar itu
tumbuh dari suatu hikmah dalam mengenali, meletakkan, dan menyikapi segala
sesuatu secara adil, yakni proporsional, berimbang, tepat, moderat, sedang, di
tengah, dan pada tempat yang seharusnya, sehingga pertimbangan mengenai
baik-buruk dan benar-salah bisa berjalan dengan semestinya; yang mana hikmah
itu lahir dari disiplin dan keteraturan dalam sikap jiwa, akal-budi, dan
badan-lahir manusia, yang dicerminkan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan;
yang mana masukan pada jiwa, akal, dan badan itu ialah ilmu, pelatihan, dan
pembelajaran yang benar, yang hak dan sejati.
Namun,
benarkah penafsiran yang demikian itu? Apatah dunia pos-modern tempat kita
hidup ini senantiasa diperikan dengan kebebasan, persamaan, dan sikap
mempertanyakan kebenaran yang ikonoklastik? Bukankah dengan demikian, semangat
dunia pos-modern ini akan bertentangan dengan konsep manusia yang teratur dan
disiplin dalam pertimbangannya akan baik-buruk dan benar-salah menurut tata
nilai tertentu dalam penafsiran tersebut? Bukankah humanisme pos-modern itu
menengahkan manusia sebagai standar segala sesuatu, sehingga segenap pokok
nilai adabi dan keadilan dapat dengan mudah bergeser oleh keinginan diri
manusia itu? Bukankah dulu LGBT dianggap sebagai penyimpangan tidak beradab,
tapi lalu mengali legalisasi di berbagai dunia Barat? Bukankah status mariyuana
bisa berubah-ubah dalam penentuan undang-undang di berbagai negara demokrasi? Apatah
semangat dunia neo-liberal ini membuat semua pokok nilai menjadi rancu dan
volatil? Tepatkah kerangka tafsir yang diuraikan tadi dalam kecenderungan
manusia dunia pos-modern yang demikian?
Jawabannya
dapatlah kita sarikan jika kita menghubungkan sila kedua itu dengan empat sila
lainnya. Demikianlah seharusnya kita memahami Pancasila itu bukan sebagai
sila-sila yang masing-masing memiliki nilai yang berdiri sendiri, karena jika
demikian, kita akan menghadapi suatu kebingungan dan dapat pula menemui
pertentangan-pertentangan antar-nilainya, terutama jika falsafah pandang kita
dalam menafsirkan satu sila berbeda dengan sila lain. Misalnya, jika kita
memahami sila kedua ini sebagai humanisme, tentu akan bertentangan dengan sila
pertama dan mungkin pula sila ketiga. Hal itu karena natur dari humanisme
demikian mendamba kesentralan manusia sebagai standar dari seluruh nilai,
sehingga nilai-nilai Ketuhanan atau agama pada sila pertama akan dengan mudah
ditabrak sesuka hati. Demikian pula, humanisme itu amat mementingkan
“kesejahteraan dan kebahagiaan” manusia di atas segalanya, yang diejawantahkan
dalam segala hal materialistis dan hedonis – makan-minum, membeli
barang-barang, dan semua kesenangan duniawi manusia yang egois dan tidak
menginginkan pengorbanan – yang sedikit-banyak akan membuat nilai-nilai sila
ketiga (jika dipandang sebagai nasionalisme) menjadi tidak relevan, karena hak negara
telah dipandang kalah dari hak manusia.
Demikianlah
seyogyanya segenap butir Pancasila itu dipandang sebagai satu kesatuan yang
jalin-menjalin, yang utuh-bertahap dalam perwujudan konseptualnya, mulai dari
falsafah paling dasar yang mengilhami konsep manusia idealnya, jalan dan metode
pengaturan yang mesti diwujudkan para manusia itu, hingga mencapai sebagian
dari tujuan berbangsa-bernegara yang riil untuk dicapai. Anggapan ini ialah
dalam susunan artian bahwa, sila kedua yang kita bahas sebelumnya merupakan
konsepsi manusia ideal yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan negara ini;
yang mana konsepsi manusia ideal itu dijiwai, diilhami, dan didasari oleh
nilai-nilai Ketuhanan yang terdapat pada sila pertama, yang hubungan keduanya
secara natural tiada dapat dipisahkan (akan dibahas di pasal selanjutnya); yang
dengan terwujudnya konsepsi manusia ideal itu, diharapkan dapat membangun dan
menjalankan suatu metode dalam menjalani urusan hidup bersama, yang dijalankan
melalui satu entitas dalam wadah persatuan, yang diatur menggunakan asas
permusyawaratan/perwakilan; yang mana itu semua digunakan untuk mewujudkan
keadilan sosial rakyat sebagai material-i-sasi atau perwujudan-riil dari sebagian
tujuan hidup berbangsa-bernegara itu. Secara sederhana, sila pertama menjiwai
upaya perwujudan sila kedua; yang dengan terwujudnya sila kedua itu, metode
yang ada pada sila ketiga dan sila keempat dapat dijalankan secara maksimal
untuk mewujudkan sila kelima, sebagai salah satu tujuan akhir hidup
berbangsa-bernegara.
Sila Pertama sebagai Fondasi Seluruh Sila Lain
Demikianlah
pembahasan selanjutnya dibangun atas dasar anggapan bahwa kelima sila itu
ikat-mengikat dalam satu kesatuan dan bahwa sila pertama ialah sumber yang
menjiwai dan menjadi titik pangkal seluruh sila yang lain. Anggapan ini
bukanlah tanpa dasar, ialah dikarenakan makna adab yang terdapat jua pada sila
kedua yang telah dibahas. Dalam pengertian adab pada uraian sebelumnya, telah
teranglah dibahas bahwa adab tiada lain ialah berkaitan dengan suatu disiplin
jiwa, akal-pikiran, dan badan-lahir manusia untuk mengenali dan menyikapi
segala sesuatu secara tepat, benar, proporsional, dan pada tempatnya, sehingga timbullah
dari dirinya suatu keteraturan untuk senantiasa menetapi jalan yang lurus-benar,
dengan sikap-perilaku yang berkeadilan terhadap setiap realitas yang didapati
dan dirasainya dalam hidup; sehingga terwujudlah dengannya suatu taraf
peri-kehidupan yang luhur secara lahir dan batin.
Dengan
demikian, pengertian adab yang seperti itu haruslah berakar pada suatu
kesadaran diri manusia untuk memahami segala realitas hidup hanya sebagai suatu
kesatuan kosmos yang berasal dari Tuhan, dikuasai oleh-Nya, dan pada akhirnya
akan kembali jua pada-Nya; suatu perasaan bahwa ia bukanlah siapa-siapa dalam
bentang luas jagat ini, tiada peduli pada segala kuasa, harta, kepintaran, dan
berupa-rupa kemampuan yang ia miliki, pada hakikatnya semua ialah milik-Nya;
suatu pengertian bahwa keberadaan, pemeliharaan, dan keberlangsungan dirinya
ialah anugerah-kebaikan dari Tuhan, sehingga menimbulkan pemahaman dalam diri
manusia itu bahwa ia berhutang-kebaikan pada-Nya, dan dengan demikian,
berimplikasi pada sikap hidup yang penuh penyerahan-diri pada aturan-aturan dan
ketetapan dari-Nya, termasuk dalam menentukan standar kebenaran dan kebaikan
serta arah hidup. Pemahaman yang demikian itu ialah yang menjadi bangunan dasar
konsep dalam istilah “ad-dīn”, yang secara sederhana, sering hanya
diterjemahkan sebagai agama. Pada langkah selanjutnya, hendaklah kita terangkan
bagaimana jalan adab itu bersumber dari “din”.
Paham
yang terkandung dalam istilah “din”, yang pada umumnya biasa dipahami serta
diartikan sebagai agama belaka, sesungguhnya tiadalah sama makna serta maksudnya
dengan paham “agama” atau “religion” seperti ditafsirkan dan dipahami dalam
sejarah keagamaan Barat, atau lain-lain agama yang bukan Islam. Namun,
mengapakah Islam itu digunakan sebagai kerangkan pandang saat ini? Jawabannya
akan diterangkan kemudian, di antaranya terkait dengan aspek historis Pancasila
serta kedudukan adab sebagai konsep yang inheren dalam Islam; tapi pada langkah
ini, kita terlebih dahulu mengkaji agama itu dalam kerangka konsep din. Maka,
apabila kita mengatakan perihal Islam dan merujuk kepadanya serta menggelarinya
sebagai suatu “agama”, justru sesungguhnya kita memaksudkan serta memahami
makna “agama” itu dengan makna dan maksud istilah “din”, termasuk segala
kandungan makna yang terdapat dalam istilah itu menurut rencana serta
keistimewaan bahasa Arab. Ini dikarenakan apa yang disebut dalam perkataan kita
sebagai “agama Islam” itu, sejatinya ialah penyempitan makna dari keseluruhan
konsep dasarnya, yang aslinya tersebut sebagai “dīn al-Islām”, yang dalam
serapan kamus bahasa Indonesia, dipadankan dengan “din Islam”.
Segala
kandungan makna yang terdapat di dalam istilah din itu merupakan bibit-bibit
atau dasar-dasar makna yang semuanya meramukan dengan seksama dan sempurnanya,
segala arti yang terkandung di dalamnya masing-masing; dan segala bibit-makna
atau makna-dasar itu, secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan paham yang
padat-mendalam serta jelas pengertiannya, sebagaimana terbayang dalam Kitab
Suci Quran dan bahasa Arab yang dimilikinya. Perkataan din berasal dari akar-kata
Arab “DYN” (dal – ya – nun), yang mengandung banyak makna-dasar yang semuanya
bersangkut-paut paham kandungannya masing-masing, sehingga jelas menayangkan
suatu gambaran pengertian yang meliputi semua kemungkinan pengertian yang
terkandung di dalamnya. Dan kandungan pengertian yang memerikan maksud paham
din, yang menyeluruhi semua makna-dasar yang terdapat di dalamnya itu,
mencerminkan “agama Islam” dengan sepenuh-lengkapnya; ialah bahwa “agama Islam”
itulah yang merencanakan dengan sempurnanya segala kemungkinan pemahaman yang
terkandung dalam makna dan maksud istilah din.
Kadang-kadang,
antara pelbagai makna-dasar istilah din itu, seolah-olah berlaku perselisihan
makna; berlaku makna yang masing-masing saling berlawanan arti dan maksudnya.
Namun begitu, kenyataan yang berdasar hanya kepada pandangan sepintas-lalu ini,
tiada harus pula mendatangkan kekeliruan dalam memahaminya. Justru karena arti
dan maksud din itu adalah suatu paham Islam yang ditafsirkan dan dihidupkan
dalam pengalaman hidup insan, maka itulah kenyataan terdapatnya
makna-makna-dasar yang seolah-olah saling berlawanan arti dan maksudnya satu
sama lain itu, sesungguhnya hanyalah membayangkan hakikat yang nyata terperi
pada diri insan sebagai sifat insani jua. Demikian karena insan itu rohani,
tapi juga jasmani; insan itu berakal, tapi juga hewani (ḥayawāni); insan
itu baik, tapi juga jahat; insan itu berilmu, tapi juga jahil; dan seterusnya.
Dan kenyataan hakikat ini, semuanya mengikrarkan dengan tegasnya betapa sangat
istilah din itu, layak menayangkan suatu pemahaman asasi dengan jelas serta
benar memerikan hakikat serta pengalaman lahir dan batin diri insani secara
tepat, tiada bercampur yang samar. Dan daya istilah din itu demikian hingga
dapat menangkap serta membayangkan arti pengalaman insan yang merupakan dasar
dan puncak hidupnya inilah yang membuktikan kejernihannya bagi mencerminkan
kebenaran.
Pelbagai
makna-dasar istilah din itu dapatlah dirumuskan kepada lima makna yang
mengandung maksud yang merujuk kepada: (1) keadaan berhutang; (2) keadaan taat
atau takluk menyerahkan diri; (3) kuasa dan daya untuk mengatur; otoritas untuk
menghukum, membalas, memberi penilaian, memberi ganjaran, memberi perhitungan,
dan memberi pertimbangan; (4) bawaan kecenderungan yang ada pada diri insan
atau kebiasaan yang menjadi adat-resam; dan (5) akidah, jalan, atau syariat
yang diikuti oleh seseorang. Dalam kenyataan yang berikut, akan saya bentangkan
suatu penjelasan yang ringkas tetapi tepat dan padat, yang akan menayangkan
maksud terakhir istilah din itu, yaitu maksud yang membawa makna serta
pengertian yang merangkumi keimanan, kepercayaan, amalan, ajaran, dan anutan
yang dihidupkan oleh kaum Muslim, baik pun secara sendirian maupun
berkumpul-gabung sebagai kaum dan umat, dan yang menjelmakan hakikatnya sebagai
agama yang digelari Islam.[58]
Kata
kerja dāna, yang terbentuk dari akar kata din, mengandung makna keadaan
berhutang dan makna-makna lain yang terkait dengan hutang-piutang. Seseorang
yang berhutang, dā’in, haruslah bersedia menaklukkan atau menyerahkan
dirinya kepada kehendak dan perintah hukum serta undang-undang mengenai hutang
piutang. Orang itu juga harus menerima syarat-syarat yang dikenakan kepadanya
oleh pemberi hutang, dā’in.
Akibatnya, orang yang berhutang itu telah mengikat dirinya dalam suatu
perjanjian dan tugas atau kewajiban untuk membayar balik atau mengembalikan
hutangnya. Keadaan terikat hutang tersebut dinamakan dayn.[59]
Dalam
keadaan berhutang serta terikat perjanjian tersebut menimbulkan kaitan dengan
perkara hukum, pertimbangan, atau penilaian terhadap sesuatu demi mencapai keputusan
yang wajar (daynūnah) dan dengan itu semua, mengikut mana yang berkenaan
padanya (idānah). Keadaan tersebut akan berlaku dalam susunan tata
tertib serta peraturan kehidupan insan
yang bermasyarakat, yang hidup berlandaskan kegiatan perniagaan dan perdagangan
dalam kota-kota atau bandar-bandar, yang dinamakan dengan kata majemuk: mudun
atau madā’in.[60]
Bentuk
tunggal dari kota atau bandar itu dinamakan madīnah. Di dalamnya,
terdapat kuasa atau otoritas yang menjalankan kerja menjatuhkan hukuman,
memberi pertimbangan dan penilaian, menetapkan kuasa pemerintahan, dan
seterusnya, yang semuanya terangkum dalam makna istilah dayyān. Semua
itu memiliki akar kata yang sama dengan kata din, yang secara sederhana sering
diterjemahkan hanya sebagai agama, padahal secara lebih lengkap dapat dianggap
sebagai suatu tatanan kehidupan adabi dengan tata susila yang luhur untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur dan tertib dalam kawalan hukum dan
undang-undang serta kuasa keadilan dan hikmat kewibawaan.[61]
Istilah
madīnah atau kota itu sendiri berkaitan erat dengan pembangunan karena
kota diwujudkan melalui pembangunan. Kegiatan membina, membangun, mendirikan
bandar-bandar, menaikkan ke taraf yang beradab, menghaluskan budi pekerti,
menimbulkan sifat insani, dan menjadikan manusia lebih berperikemanusiaan
terangkum dalam istilah maddana, yang dengan demikian tidak hanya
mencakup pembangunan fisik. Kata kerja maddana tersebutlah yang
membentuk istilah tamadun.[62]
Kata
tamadun dapat diartikan sebagai keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang
telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi
seluruh masyarakatnya. Dengan begitu, kata tamadun dapat dimaknai sebagai
peradaban, yang juga berarti negeri berlandaskan kebudayaan, kebudayaan
berlandaskan negeri, atau suatu tempat yang dibangun atas dasar din.[63]
Keseluruhan istilah tersebut memiliki akar yang sama dengan istilah din,
sehingga peradaban memang terkait dengan din, di mana din Islam menjadi dasar
tegaknya suatu tamadun atau peradaban masyarakat yang madani.
Apabila
kita bayangkan saja dalam renungan-pandang-akal perihal gambaran suatu keadaan
yang menayangkan berlakunya hukum dan undang-undang serta keadilan dan
kewibawaan, dan suasana adab serta tata-susila luhur masyarakat dan tamadun –
yang semuanya ini terkandung sebagai rumusan yang jernih dalam paham din
seperti yang telah diringkaskan di atas – maka sudah barang tentulah harus
tampak pula suatu keadaan diri insani tertentu yang wajib ada sebelumnya. Yakni,
harus ada terlebih dahulu suatu gaya dan cara berkelakuan pada diri insan,
suatu perangai, yang selari, seia, sebati dengan apa yang dibayangkan olehnya
pada dirinya sehingga terbayang pula pada hukum dan undang-undang, keadilan dan
kewibawaan, suasana adab serta tata-susila-luhur masyarakat, dan tamadun serta
kehalusan budi-pekerti.
Harus
ada terlebih dahulu perangai, cara-gaya berkelakuan, atau keadaan hidup serta
kejadian diri: suatu tabiat yang sesuai dengan apa yang dijelmakan olehnya
sebagai keadaan hidup lahiriahnya, sehingga keadaan hidup lahir yang tampak itu
mencerminkan sesuatu yang sudah teradat, sudah jadi pada diri, sudah menjadi
adat-resam diri insani, sudah membayangkan tabiatnya. Maka, dari kenyataan
hakikat inilah, kita dapat memahami keterkaitan yang benar-benar munasabah yang
menimbulkan dari kandungan paham din itu, makna-dasar yang keempat tersebut:
bawaan kecenderungan yang sedia ada pada diri insan, yang sudah menjadi
kebiasaan baginya, yang sudah menjadi adat-resamnya sehingga dapat digelari
sebagai perangainya yang sebenarnya, sebagai tabiatnya.
Perangai
dan tabiat asas insani yang sudah menjadi adat-resam ini, tiada lain adalah
kecenderungan asasi diri insan untuk memenuhi suatu disiplin-keteraturan dalam
sikap jiwa, akal-pikiran, dan badan-lahir tertentu, yang akan membawanya menuju
kehidupan dengan taraf adabi yang luhur, suatu tamadun yang madani. Perangai,
tabiat, dan adat-resam yang mengasas dalam diri insan itulah yang biasa kita
namakan sebagai fitrah manusia, suatu kecenderungan asasi-alami yang sesuai
dengan jati-dirinya yang suci dan luhur. Dengan begitu, segala tata-aturan dan
keilmuan yang sejati ialah yang menuntun manusia untuk menetapi fitrahnya itu,
yakni dengan menetapi petunjuk dari nilai-nilai din, yang padanya itu terdapat
tuntunan dari Sang Dayyan, yang menjadi asal keberadaan dan
keberlangsungan manusia itu.
Segala
penyimpangan dari din adalah penyelewengan manusia terhadap tuntunan kesejatian
yang memurnikan fitrahnya itu, sehingga kondisi yang menjadi prasyarat
terbentuknya diri yang beradab tiada lagi terbentuk. Degan demikian, peradaban
yang terbentuk dari diri yang berlepas dari tuntunan din itu ialah peradaban
yang tiada lagi madani, yang akan membawa manusia itu kepada kerusakan akibat
kebingungan dan kesalahan penentuan standar, penilaian, dan pertimbangan. Peradaban
yang tiada lagi madani itu ialah peradaban berdasar nalar-akal dan hasrat-nafsu
manusia belaka, tanpa tuntunan kebaikan dan kebenaran abadi, dengan nilai-nilai
fundamen yang mudah bergeser dalam bentang dinamika zaman. Peradaban seperti
itu pula, sungguh pun ia mampu menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan,
hanyalah kesejahteraan dan kebahagiaan parsial belaka: kaya tapi gampang bunuh
diri, makmur tapi tingkat stres tinggi, berkuasa tapi zalim, dan seterusnya.
Pada
takat ini, telah diuraikanlah kelima makna kata din yang disebutkan sebelumnya,
dan bagaimana ia bertalian-erat dengan konsep adab. Hal itu karena din itu
sendiri ialah suatu kesadaran dalam diri manusia bahwa ia berhutang kepada
Allah, Sang Dayyan, yang telah memberikannya kehidupan serta menjaga keberlangsungan
hidupnya; yang dengan kesadaran itu, menumbuhkan suatu tanggung jawab untuk
membayar-balik hutangnya, dalam jalan menyerahkan-diri atau tunduk pada segenap
otoritas, penilaian, pertimbangan, dan tuntunan Tuhan, yang jika diejawantahkan
secara konsekuen, akan mewujudkan suatu pribadi yang berkomitmen penuh terhadap
keseluruhan tata-aturan itu, sehingga ia akan hidup memenuhi kecenderungan
fitrahnya yang luhur, baik secara sendirian maupun sebagai umat; yang dengan
demikian, pada akhirnya akan mewujudkan tata masyarakat yang madani, suatu
peradaban yang dibangun atas dasar din, suatu tamadun, suatu tata kehidupan
adabi dengan tata-susila yang luhur dengan kehidupan masyarakat yang teratur
dalam kawalan hukum dan undang-undang serta kuasa keadilan dan hikmat
kewibawaan.
Demikianlah
konsep adab dan din berjalin-rekat. Tampak nyata pula bahwa din itu mengilhami
dan menjiwai konsep adab sebagai perwujudan ideal manusia yang mengemban wasiat/tugas/amanah
din itu. Konsep din inilah yang ada pada sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang
Maha Esa” ialah suatu inti pokok dari risalah din itu. Dengan demikian, dapat
diterangkanlah bagaimana sila pertama itu menjadi dasar dari sila kedua. Namun,
ini baru menjawab pertanyaan soal hubungan antara adab dengan din, atau sila
kedua dengan sila pertama. Pertanyaan mengenai kenapa kerangka pandang din ini,
yaitu kerangka pandang yang bersesuaian dengan falsafah hidup Islam, digunakan
dalam tinjauan adab belum dijawab. Memanglah kerangka din ini cocok digunakan
dalam penyelidikan hubungannya dengan adab, tapi apakah kerangka din ini secara
langsung dan inheren merupakan kerangka pandang Islam, dan tepatkah ia
diterapkan pada sila pertama?
Sekarang,
makna din itu dapat dihubungkan secara erat dengan makna Islam. Islam memiliki
sejumlah lingkup makna: (1) berserah diri, terkait dengan aslama, istaslama,
dan istislam; (2) mengakui, menyerahkan kuasa, dan menerima sesuatu, terkait
dengan sallama, yusallimu, taslīm; (3) damai, sejahtera,
stabilitas, keselamatan, dan harmoni, terkait dengan silm dan salām;
(4) berada dalam kondisi yang baik, tidak rusak, tidak cacat, menjadi benar,
lurus, penuh, lengkap, dan integral, terkait dengan salīm; (5) menyelamatkan,
memperbaiki, menyatukan, dan merekonsiliasi, terkait dengan sallama dan sālama;
dan (6) tangga, sesuatu yang bertingkat, terkait dengan sullam.[64]
Dengan
demikian, makna Islam dapat dituangkan sebagai suatu bentuk penyerahan diri dan
pengakuan serta penerimaan terhadap otoritas Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang
tiada memiliki sekutu dan berhala perantara, tiada memiliki anak, tiada menjadi
anak, dan tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya, sebagai satu-satunya Ilahi
pemilik otoritas hakiki, dalam mengatur kehidupan seseorang, sehingga hidupnya
dapat diarahkan kepada jalan yang lurus, dengan kebaikan dan keadilan yang
sempurna dan integral, yang diupayakannya secara bertingkat sesuai kemampuan,
agar manusia itu dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan pribadi, serta
perbaikan masyarakat dan lingkungan.
Cocoklah
makna Islam yang demikian itu dihubungkan dengan makna din yang telah dibahas
sebelumnya, dengan pokoknya berjalin pada pengakuan atau penyerahan diri kepada
otoritas Allah. Itu karena dalam din Islam, keberadaan manusia di dunia ini
merupakan suatu karunia Allah, berikut juga segenap kondisi yang memelihara
kehidupan manusia itu, seperti jasad, makanan, udara, air, sinar matahari, dan
lain-lain. Dengan demikian, manusia itu dipandang berhutang kebaikan kepada
Allah, yang disebut sebagai ad-Dayyān, Sang Pemberi Hutang.[65]
Namun,
karena manusia tidak memiliki dan menguasai apa pun, fakir di hadapan Allah
Yang Maha Kaya, ia tidak punya pilihan untuk membayar hutang itu selain dengan menyerahkan
dirinya kepada Allah. Dengan menyerahkan diri pada Allah, manusia mengakui
otoritas Allah atas dirinya, sehingga hidupnya, matinya, ibadahnya, dan segala
sesuatu yang ia lakukan diperuntukkan bagi Allah.[66]
Dengan begitu, hidupnya pun diupayakannya agar senantiasa berada dalam tuntunan
dan ketentuan Allah, menerima standar-Nya tentang kebaikan dan keburukan, serta
memperjuangkan cita-cita yang sesuai dengan jalan-Nya.
Segenap
tuntunan, ketentuan, dan jalan Allah yang diikuti manusia itulah din Allah,
yang dengan sendirinya memiliki keselarasan dengan kecenderungan kebaikan alami
manusia (fitrah insani). Sederhananya, dengan mengikuti din Allah itu, hidup
manusia akan menjadi lebih insani, tidak diperbudak oleh nafsu hewani dalam
dirinya, maupun ritme mekanis masyarakat pasarnya. Dengan demikian, akan
terbentuk pribadi manusia yang utuh, insan kamil.[67]
Pribadi-pribadi itu berkumpul membentuk keluarga dan komunitas, yang dalam
skala lebih besar, akhirnya membentuk suatu masyarakat.
Karena
pribadi sebagai unit terkecil masyarakat itu menjalankan hidupnya sesuai dengan
din, maka komunitas dan masyarakat yang dibentuknya juga akan tumbuh
berdasarkan din tersebut. Masyarakat demikian adalah masyarakat yang madani,
masyarakat yang dibangun berbasis din. Di tengah masyarakat madani itulah, buah
peradaban akan terbangun, sehingga berkembanglah tamadun. Sekali lagi, din
Islam, adab, peradaban, dan tamadun memiliki kaitan yang erat.
Selain
itu, redaksional dan latar historis sila pertama memanglah demikian lekat
dengan konsepsi falsafah hidup Islam. Ketuhanan dalam bahasa Indonesia bermakna
“(1) sifat keadaan Tuhan; (2) segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan; (3)
kepercayaan kepada Tuhan; dasar percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa”.[68]
Sedangkan kata esa bermakna “(1) tunggal; satu; (2) bersifat tunggal, tidak
bersekutu”.[69] Dengan
demikian, “Ketuhanan yang Maha Esa” berarti suatu dasar kepercayaan bahwa sifat
Tuhan itu, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan-Nya ialah berdasarkan kepada
keesaan, yaitu bahwa Tuhan adalah esa, hanya ada satu, tiada melekat pada-Nya
suatu sekutu apa-pun. Sekutu di sini berarti pihak-pihak lain yang diikutkan
atau digabungkan dengan-Nya. Artinya, penggunaan berhala atau perantara dalam
peribadatan kepada-Nya termasuk suatu tindakan menyekutukan, demikian pula pelekatan
sifat terbagi pada diri-Nya dalam substansi apa pun, entah itu keluarga atau
rekan-kolega dalam hal otoritas Ketuhanan.
Demikianlah
ajaran keesaan Tuhan itu secara murni dan konsekuen menjadi pokok ajaran dari
din Islam, ialah suatu yang disebut sebagai tauhid, berakar dari kata ahad,
yang berarti satu, sehingga demikian tauhid itu bermakna pengesaan Tuhan. Tiada
syak, tiada keraguan, tiada kekalutan apa pun yang membantah dan menentang bahwa
din Islam itulah yang mengajarkan pengesaan Tuhan secara murni dan konsekuen. Seorang
seperti Tan Malaka, seorang yang dianggap kiri sekalipun, mengakui seutuhnya
hal ini. Tulisnya dalam bukunya, “Madilog”, yang terkenal itu sebagai berikut.
“Demikianlah pada (ajaran) Muhammad SAW ‘ketunggalan’ Tuhan itu, keesaan Tuhan
itu, sampai ke puncak, tak ada kesangsian.”[70]
Selain
itu, telah nyatalah pula betapa sejarah dari sila pertama itu, ialah berpangkal
pada redaksional sebelumnya, yaitu yang ditetapkan oleh Panitia Sembilan pada
22 Juni 1945, yang pula disetujui oleh wakil non-muslim di dalamnya, Mr. Alexander
Andries Maramis. Walaupun kemudian redaksional itu diubah jua mengingat
dinamika keadaan yang terjadi, tapi tetaplah nafas awal yang demikian itu,
tiadalah salah bila diterapkan dalam pemaknaan dan penghayatan terhadap sila
itu. Janganlah dicela bilamana seorang menyatakan bahwasanya makna sila pertama
itu ialah tauhid. Namun tiadalah pula dapat dipaksakan pemahaman itu kepada
tiap orang, terutama sekali kepada saudara-saudari kita yang non-muslim.
Sebagaimana dalam ajaran Islam itu sendiri, “lā ikrāha fi-d-dīn” (tiada
paksaan untuk memeluk din).
Begitu
pulalah kita tiada perlu berlarut-larut dalam perdebatan mengenai penghapusan
tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang lalu menjiwai Pembukaan Undang-undang
Dasar itu dan diformulasikan kepada bentuk Pancasila yang sekarang. Biarlah ia
menjadi suatu bahan refleksi sejarah. Tiadalah perlu bagi kita suatu
perselisihan yang memecah-belah dari mana bersumber dari perdebatan akan tujuh
kata itu. Ia pun mesti dipahami bahwa terdapat orang muslim pula yang tiada
menyetujui konsep itu dikembalikan saat ini, yaitu mereka yang mengambil
kerangka pandang sekuler dalam hidupnya.
Namun,
tiadalah kita boleh lupa latar historis dari sila itu, agar napas jiwanya
tetaplah hidup menyala di dada umat ini, dan teranglah kita mengingat
sebagaimana yang dinyatakan oleh Mr. Alamsyah Ratu Prawiranegara itu,
bahwasanya Pancasila ini ialah suatu hadiah besar umat Islam bagi republik ini.
Cukuplah bagi kita dalam tulisan ini, untuk menjadikannya hujah bagi dasar
pemahaman kita, bahwa sila pertama ini dijiwai oleh din sebagaimana yang kita
jelaskan sebelumnya. Dan dengan demikian, telah cocoklah konsep penafsiran
kita, bahwa sila pertama yang berdasar din Islam itu, ialah sebagai dasar bagi
sila kedua yang memuat konsep adab yang inheren dalam din itu. Dengan begitu
pula, ialah sila pertama itu sebagai dasar jua bagi sila-sila lain, sebagaimana
ia menjiwai sila kedua dalam bahasan sebelumnya.
Sila Ketiga dan Mosi Integral
Kata
persatuan berakar dari kata dasar satu yang bermakna tunggal. Sementara itu, persatuan
berarti “(1) gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang
sudah bersatu; (2) perserikatan; serikat; (3) perihal bersatu”.[71]
Secara sederhana, persatuan adalah suatu entitas yang merupakan gabungan atau
kumpulan dari banyak hal dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Persatuan
Indonesia tumbuh dari suatu pengalaman sejarah yang sama, yaitu bahwa
entitas-entitas geopolitik yang ada sebelumnya – kerajaan-kerajaan lokal –
tidak dapat menghadapi fenomena sejarah yang muncul kemudian, yaitu kolonialisme.
Karena itulah, muncul suatu gelombang gerakan baru dalam spektrum yang lebih
besar dari kerajaan-kerajaan itu, yang bernama bangsa dan Republik Indonesia.
Namun,
bangsa dan republik yang bersatu itu tidaklah selalu mengambil bentuk negara
kesatuan. Hal ini banyak kita dapati pada republik-republik modern yang masih
maujud sampai saat ini, seperti Amerika Serikat yang berbentuk negara federasi.
Demikian pula arti dari persatuan itu sendiri malah memberi ruang bagi suatu
bentuk gabungan perserikatan, suatu negara serikat. Namun, satu hal yang khas
dalam khazanah republik ini ialah, secara konsekuen, selalu terdapat pihak yang
memperjuangkan negara kesatuan sebagai bentuk ideal republik ini. Meskipun
karena satu dan lain hal kita pernah mengalami periode Republik Indonesia
Serikat (RIS), berbagai upaya untuk kembali kepada khitah awal sebagai negara
kesatuan tetap dilakukan.
Sejatinya,
pengupayaan bentuk negara kesatuan yang konsekuen itu amat lekat dengan
konsepsi pemahaman tafsir Pancasila menurut kerangka pandang din, karena orang
yang menjunjung tinggi din, orang yang beradab itu, termasuklah orang yang
menjunjung tinggi persatuan, senantiasa berupaya menyusun suatu umat, suatu
terminologi serapan dari bahasa Arab pula, yang dalam makna dasar umat itu,
terdapatlah unsur kesadaran untuk bersatu dalam ikatan baru yang melebihi
ikatan primordial, melebihi sekadar kaum, yang pula diserap dari bahasa Arab.
Tidak
perlulah kita berpanjang-lebar membahas bukti dari hal ini. Satu contoh
peristiwa sejarah telah cukup membuktikan bahwa, pelopor kembalinya Indonesia
menuju bentuk negara kesatuan, setelah sempat menjadi RIS, tiada lain tiada
bukan ialah seorang yang secara murni dan konsekuen memandang Pancasila itu
menurut falsafah hidup din. Ia mengajukannya dalam pidatonya di parlemen pada
tanggal 3 April 1950, suatu pidato yang berisi desakan pembentukan negara
kesatuan, yang di kemudian hari dikenal sebagai “Mosi Integral”. Orang itu
ialah Mohammad Natsir, seorang tokoh Masyumi.
“Berhubung
dengan ini, saya ingin memajukan satu mosi kepada Pemerintah yang bunyinya
demikian:
Dewan
Perwakilan Rakyat Sementara RIS dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang
sangat perlunya penyelesaian yang integral dan program-a-tis terhadap akibat
-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu yang
akhir-akhir ini.
Memperhatikan:
Suara
rakyat dari berbagai daerah, dan mosi-mosi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
saluran dari suara-suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda
dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia.
Kompak
untuk menampung segala akibat-akibat yang tumbuh karenanya dan
persiapan-persiapan yang untuk itu harus diatur begitu rupa dan menjadi program
politik dari Pemerintah yang bersangkutan dan dari Pemerintah RIS.
Politik
peleburan dan penggabungan itu membawa pengaruh besar tentang jalannya politik
umum di dalam negeri dan pemerintahan di seluruh Indonesia.
Memutuskan:
Menganjurkan
kepada Pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau
sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang
hangat yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu yang
akhir-akhir ini dengan cara integral dan program yang tertentu.”
Demikianlah
Natsir, sebagai anak kandung falsafah hidup Islam itu di tanah air kita,
menjadi seorang pemersatu menurut Mosi Integral yang ia ajukan.
Sila Keempat sebagai Mekanisme Pengaturan
Sila
keempat memuat sejumlah konsep pokok, yang mencakup kerakyatan, hikmat-kebijaksanaan,
permusyawaratan, dan perwakilan. Kata rakyat diserap dari bahasa Arab “raʿiyat”,
demikian pula hikmat berasal dari kata “ḥikmah”. Kata musyawarah juga
diserap dari bahasa Arab “musyāwarah”, “musywarah”, atau “masyūrah”
yang memiliki pokok kata yang menjalin bentuk “syura”. Kata wakil juga diserap
dari bahasa Arab “wakīl” yang berkaitan dengan kata kerja “wakkala”.
Sementara itu, kata bijaksana diserap dari bahasa Jawa “wicaksana”.
Kata
rakyat dalam bahasa Indonesia bermakna “(1) penduduk suatu negara; (2) orang
kebanyakan; orang biasa; (3) pasukan (bala tentara); (4) anak buah; bawahan”.[72]
Kata kerakyatan berarti “(1) segala sesuatu yang mengenai rakyat; (2)
demokrasi; (3) kewarganegaraan”.[73]
Kata rakyat menurut serapan bahasanya “ra’iyat” bermakna “(1) “raʿāyā”,
yaitu kongregasi; perkumpulan orang; khalayak; massa; (2) “qaṭīʿ ”,
yaitu kerumunan; kelompok; dan (3) “muwāṭin”, yang warga; penduduk.
Kerakyatan dapat dipandang sebagai suatu sistem untuk mengakomodasi kehendak
rakyat, suatu pemerintahan rakyat, yang jamaknya diterjemahkan sebagai
demokrasi. Natsir mengatakan, “Pemerintah yang timbul dari rakyat dan untuk
rakyat dan yang terdiri dari pemimpin perjuangan kemerdekaan sendiri, tentu
tahu benar-benar dan sudah dapat merasakan, apa yang hidup dalam keinginan
rakyat itu.”[74]
Kata
hikmat dimaknai sebagai “(1) kebijakan; kearifan; (2) kesaktian (kekuatan
gaib)”.[75]
Menurut akar kata Arabnya, hikmah memiliki makna “(1) “ḥaṣāfah”, yang berarti
kebijaksanaan, pandangan jauh ke depan, wawasan, kecerdikan, keadilan
pandangan, pemikiran insani; (2) “falsafah”, yang berarti falsafah, filsafat,
atau filosofi; (3) “qawl ma’tsūr”, yang berarti pepatah, perkataan
bijak, nasihat, aforisme, pandangan; (4) kondisi berkepala dingin, kelayakan,
kelihaian, dan penilaian yang sehat. Kata kebijaksanaan berarti “(1) kepandaian
menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); (2) kecakapan
bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya”.[76]
Secara
sederhana, hikmat-kebijaksanaan bermakna suatu kebijaksanaan yang tumbuh dari
proses berpikir yang sehat dan proporsional, dengan mendudukkan segala sesuatu
menurut tempat yang semestinya, dalam suatu disiplin pandangan yang layak menurut
wawasan yang sejati. Demikianlah dapat terlihat eratnya hubungan hikmat-kebijaksanaan
(hikmah) ini dengan konsep adab dan ilmu yang telah dibasah sebelumnya; yaitu
ilmu yang benar akan membawa pada hikmah dalam mengambil keputusan atau
pandangan, yang pada akhirnya membentuk adab yang luhur.
Kata
musyawarah berarti “pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas
penyelesaian masalah; perundingan; perembukan”.[77]
Akar kata serapannya, syura, memiliki arti “(1) kegiatan membahas,
mendiskusikan, atau mempertanyakan sesuatu; penalaran metodis; debat; beradu
argumen; mempertahankan gagasan; (2) pertukaran pandangan; upaya konsiderasi; pemberian
opini terhadap sesuatu; (3) nasihat, konsultasi, sugesti; (4) studi atau
investigasi yang hati-hati. Secara sederhana, musyawarah adalah pengambilan
keputusan atau pemecahan masalah melalui pembahasan bersama dengan saling
bertukar pikiran dan mempertahankan gagasan masing-masing hingga tahap
tertentu, untuk mencapai keseimbangan gagasan yang disepakati bersama.
Musyawarah
adalah sistem pengambilan keputusan yang dirembesi prinsip-prinsip adab, karena
pertukaran gagasan dalam musyawarah merupakan suatu pengujian kualitas pikiran,
sehingga berkaitan erat dengan adab. Hal ini tentu amat berbeda dengan
pengambilan keputusan melalui voting atau suara terbanyak, di mana pikiran
semua pihak dianggap bernilai sama, entah dia ahli atau tidak, bodoh atau
berilmu, awam atau berpengalaman, dan seterusnya, segala kualitas yang penting
dalam penentuan gagasan yang demikian, tiada dipertimbangkan dalam voting itu,
karena satu suara bernilai satu, sehingga lebih rawan menghasilkan keputusan
yang salah, walaupun dipilih secara mayoritas. Dengan demikian, musyawarah
sangat lekat dengan adab, dan nyatanya, ia sendiri merupakan bagian ajaran din
Islam yang di dalamnya inheren konsep adab itu. “Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu.”[78]
“ ... (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat,
sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”[79]
Kata
wakil bermakna “(1) orang yang dikuasakan menggantikan orang lain; (2) orang
yang dipilih sebagai utusan negara; duta; (3) orang yang menguruskan
perdagangan dan sebagainya untuk orang lain; agen; (4) jabatan yang kedua
setelah yang tersebut di depannya”.[80]
Kata perwakilan diartikan sebagai “(1) segala sesuatu tentang wakil; (2)
kumpulan atau tempat wakil-wakil; (3) (kantor, urusan, dan sebagainya) wakil
suatu negara sebelum ada duta; (4) (tempat atau kantor) wakil usaha; (5)
seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan
bertindak atas nama”.[81]
Kata kerja “wakkala” dalam bahasa Arab bermakna “memberikan kuasa pada suatu
pihak, menguasakan, menunjuk representasi, memberikan kepercayaan pada
seseorang”. Secara sederhana, perwakilan dapat diartikan sebagai pemberian atau
pendelegasian kuasa dari rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kepada
pihak-pihak yang ditunjuknya untuk meneruskan kepentingannya dalam hidup
bernegara.
Dengan
demikian, sila keempat ini dapat kita maknai sebagai suatu sistem pemerintahan
dan akomodasi kehendak rakyat, yang dilakukan melalui model delegasi kedaulatan
dan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya, ke
dalam suatu majelis tempat mereka bermusyawarah, membahas persoalan tersebut
untuk mencapai suatu permufakatan. Sistem perwakilan rakyat ini bolehlah
diterjemahkan ke dalam demokrasi, tapi asas pengambilan kebijakan yang dipakainya
ialah melalui musyawarah, yang lebih memberi ruang bagi seleksi gagasan secara
kualitatif alih-alih menyamaratakan nilai dan kualitas pikiran setiap orang
dengan voting. Konsep musyawarah itu dengan sendirinya mengakui adanya muzakarah
atau perbedaan pendapat yang ada. Penyelesaian perbedaan pendapat itu dipandu
oleh hikmah pemikiran yang luhur dan beradab.
Demikianlah
sila keempat ini merupakan suatu metode yang digunakan oleh manusia yang
beradab yang telah dibahas sebelumnya, guna mewujudkan keadilan pada sila
kelima. Metode pada sila keempat ini mengharuskan adanya suatu persatuan, yang
menjadi metode atau jalan yang ditempuh untuk menuju musyawarah-mufakat itu.
Dengan demikian, metode atau jalan dari sila ketiga pulalah satu kesatuan
dengan jalan sila keempat ini. Dan kedua jalan atau metode itu, ialah jalan
atau metode yang hanya akan dapat diwujudkan dengan seutuhnya oleh manusia yang
beradab, konsep manusia ideal pada sila kedua.
Sila Kelima sebagai Material-isasi Tujuan Akhir Seluruh
Sila
Kata
keadilan sebagaimana pembahasan sebelumnya ialah berpokok pada
proporsi-o-nal-i-tas dalam menetapkan dan melakukan pembagian kadar dan
pertimbangan. Dengan demikian, keadilan tidak selalu dipahami sebagai pembagian
yang dipukul sama rata. Pembagian secara adil di sini tidaklah selalu berarti
sama secara kuantitas, tetapi lebih kepada ketepatan, nilai, kondisi intrinsik,
kebenaran, dan utilitas, sehingga bagian yang secara kuantitas lebih kecil,
dapat memiliki kadar yang sama berat dengan bagian yang secara kuantitas lebih
besar. Keadilan sosial dengan demikian mestilah dipandang menurut asas proporsional
berdasarkan suatu ukuran pertimbangan tertentu.
Nilai
keadilan ini secara inheren merupakan bagian dari ajaran din Islam itu. Orang-orang
yang beriman, yang menjunjung tinggi din, dan beradab itu diperintahkan untuk “senantiasa
menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil (kepada mereka).
Berbuat adillah karena ia lebih dekat dengan takwa.”[82]
Dengan demikian, sifat keadilan – sebagaimana pula pada pembahasan sila kedua –
melekat pada manusia yang beradab, sehingga keadilan secara sosial, dalam taraf
hidup masyarakat, merupakan salah satu tujuan dari membangun tamadun atau
peradaban, meski bukan satu-satunya tujuan. Dan karena keadilan sosial itu bisa
tampak dan dirasakan, maka ia dapat dianggap sebagai material-isasi tujuan dari
manusia yang beradab itu dalam menjalani metode persatuan dan kerakyatan yang
dibahas sebelumnya, yang sekali lagi, seluruhnya diilhami oleh nafas din dari
sila pertama.
Kesimpulan
Demikianlah
seyogyanya segenap butir Pancasila itu dipandang sebagai satu kesatuan yang
jalin-menjalin, yang utuh-bertahap dalam perwujudan konseptualnya, mulai dari
falsafah paling dasar yang mengilhami konsep manusia idealnya, jalan dan metode
pengaturan yang mesti diwujudkan para manusia itu, hingga mencapai sebagian
dari tujuan berbangsa-bernegara yang riil untuk dicapai. Anggapan ini ialah
dalam susunan artian bahwa, sila kedua memuat konsepsi manusia yang adil dan
beradab sebagai konsepsi manusia ideal yang mesti diwujudkan dalam
penyelenggaraan negara ini; yang mana konsepsi manusia ideal itu dijiwai,
diilhami, dan didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan yang terdapat pada sila
pertama, yang hubungan keduanya secara natural tiada dapat dipisahkan; yang
dengan terwujudnya konsepsi manusia ideal itu, diharapkan dapat membangun dan
menjalankan suatu metode dalam menjalani urusan hidup bersama, yang dijalankan
melalui satu entitas dalam wadah persatuan, yang diatur menggunakan asas
permusyawaratan/perwakilan; yang mana itu semua digunakan untuk mewujudkan
keadilan sosial rakyat sebagai material-isasi atau perwujudan-riil dari sebagian
tujuan hidup berbangsa-bernegara itu. Secara sederhana, sila pertama menjiwai
upaya perwujudan sila kedua; yang dengan terwujudnya sila kedua itu, metode
yang ada pada sila ketiga dan sila keempat dapat dijalankan secara maksimal
untuk mewujudkan sila kelima, sebagai salah satu tujuan akhir hidup
berbangsa-bernegara.
[1] Aziz Anwar Fachrudin. “Polemik Tafsir Pancasila”. Laporan Kehidupan
Beragama di Indonesia. Edisi III, Januari 2018, Program Studi Agama dan
Lintas Budaya, CRCS, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, UGM, ISBN
978-602-50445-3-3, hal.3
[2] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.19
[3] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.3
[4] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.3
[5] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.3-4
[6] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.4
[7] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.4-5
[8] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.5
[9] Aziz Anwar Fachruddin, Ibid., hal.5
[10] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.6
[11] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.6
[12] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.6-7
[13] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.7
[14] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.7
[15] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.7-8
[16] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.8
[17] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.8
[18] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.8-9
[19] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.9-10
[20] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.10-11
[21] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.11
[22] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.11-12
[23] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.12
[24] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.12
[25] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.12
[26] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.13
[27] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.13
[28] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.13-14
[29] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.14
[30] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.14-15
[31] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.15
[32] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.15
[33] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.16
[34] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.16
[35] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.16-17
[36] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.17
[37] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.17-18
[38] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.18
[39] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.18
[40] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.18
[41] Aziz Anwar Fachrudin, Ibid., hal.19
[42] Said Zulfikar. Manusia (Kompasiana, 25 Januari 2016, https://www.kompasiana.com/saidnazulfiqar/56a3ca9981afbd2d0917e45d/manusia,
diakses pada 11 Mei 2020)
[43] KBBI daring, https://kbbi.web.id/manusia,
diakses pada 12 Mei 2020
[44] KBBI daring, https://kbbi.web.id/akal,
diakses pada 12 Mei 2020
[45] KBBI daring, https://kbbi.web.id/budi,
diakses pada 12 Mei 2020
[46] KBBI daring, https://kbbi.web.id/akal,
diakses pada 12 Mei 2020
[47] KBBI daring, https://kbbi.web.id/budi,
diakses pada 12 Mei 2020
[48] Said Zulfikar, op cit.
[49] Q.S. 2: 132
[50] KBBI daring, https://kbbi.web.id/adil,
diakses pada 12 Mei 2020
[51] Edward William Lane. An Arabic-English Lexicon. Book I – Part 5.
(London: William and Norgate, 1874), hal 1972-1975, berdasarkan Lisanul Arab
Ibnu Manẓur.
[52] Edward William Lane, Ibid.
[53] Edward William Lane, Ibid.
[54] KBBI daring, https://kbbi.web.id/adab,
diakses pada 12 Mei 2020
[55] Edward William Lane. An Arabic-English Lexicon. Book I – Part 1.
(London: William and Norgate, 1863), hal 34, berdasarkan Lisanul Arab Ibnu Manẓur.
[56] Naquib al-Attas. Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993),
hal.105
[57] Naquib al-Attas, Ibid., hal.106-110
[58] Hamid F. Zarkasyi. “Tamaddun sebagai Konsep Peradaban Islam”. Tsaqafah
Jurnal Peradaban Islam. Vol. 11, No. I, Mei 2015, hal. 5-6. [DOI: http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i1.251 ]. Lihat juga Naquib
Al Attas. Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak (Kuala Lumpur: IBFIM,2013) hal.5
[68] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketuhanan,
diakses pada 12 Mei 2020
[69] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/esa,
diakses pada 12 Mei 2020
[70] Tan Malaka. Madilog (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1951), hal.389
[71] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persatuan,
diakses pada 13 Mei 2020
[72] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rakyat,
diakses pada 12 Mei 2020
[73] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerakyatan,
diakses pada 12 Mei 2020
[74] Natsir, op cit., hal.6
[75] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hikmat,
diakses pada 12 Mei 2020
[76] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijaksanaan,
diakses pada 12 Mei 2020
[77] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyawarah,
diakses pada 12 Mei 2020
[78] QS. 3: 159
[79] QS. 42: 38
[80] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakil,
diakses pada 12 Mei 2020
[81] KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perwakilan,
diakses pada 12 Mei 2020
[82] QS. 5: 8, lihat juga QS. 16:90

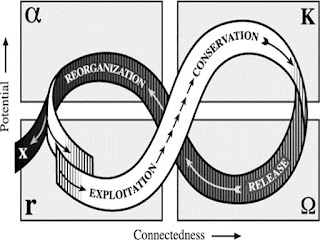

Comments
Post a Comment